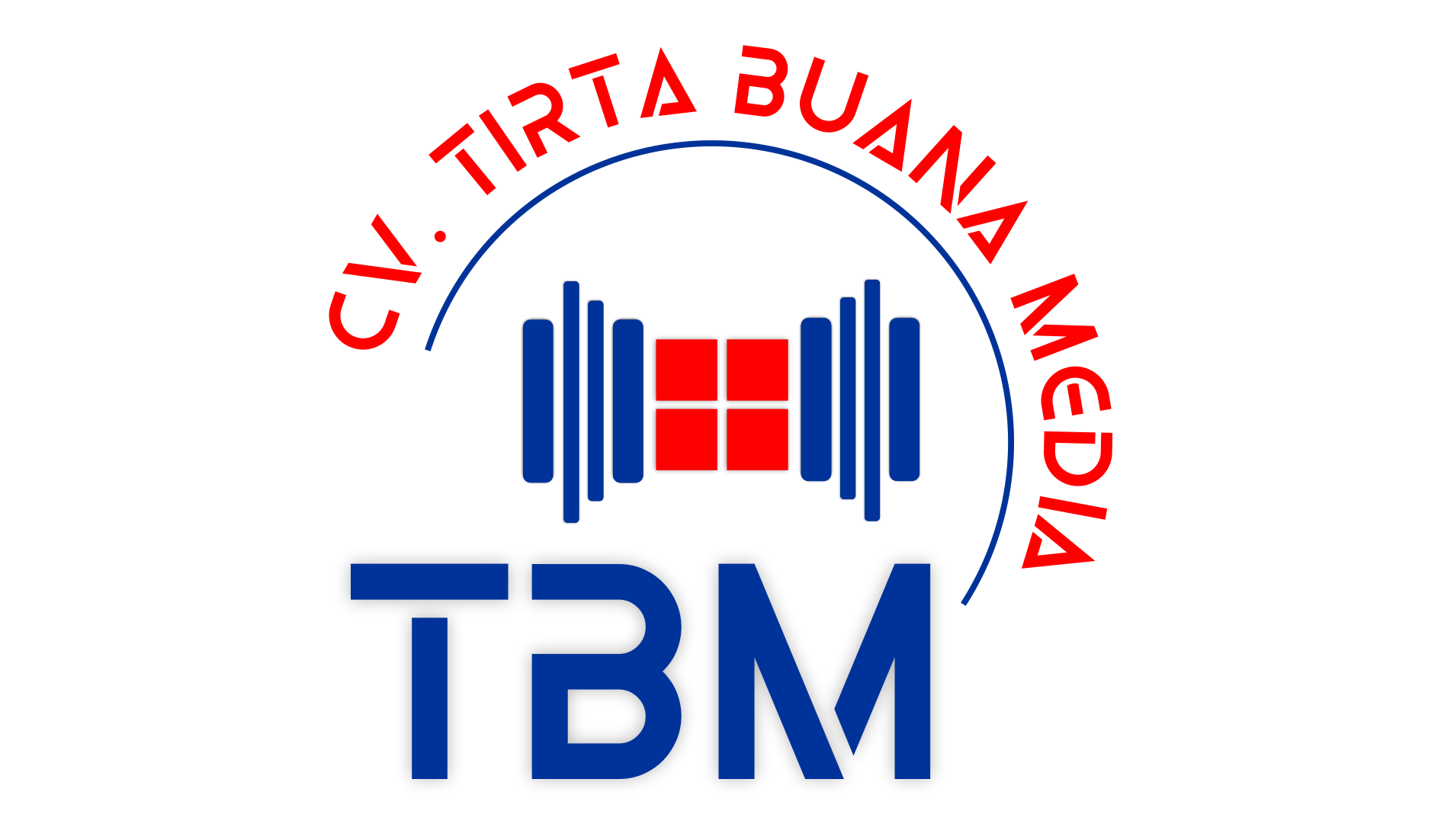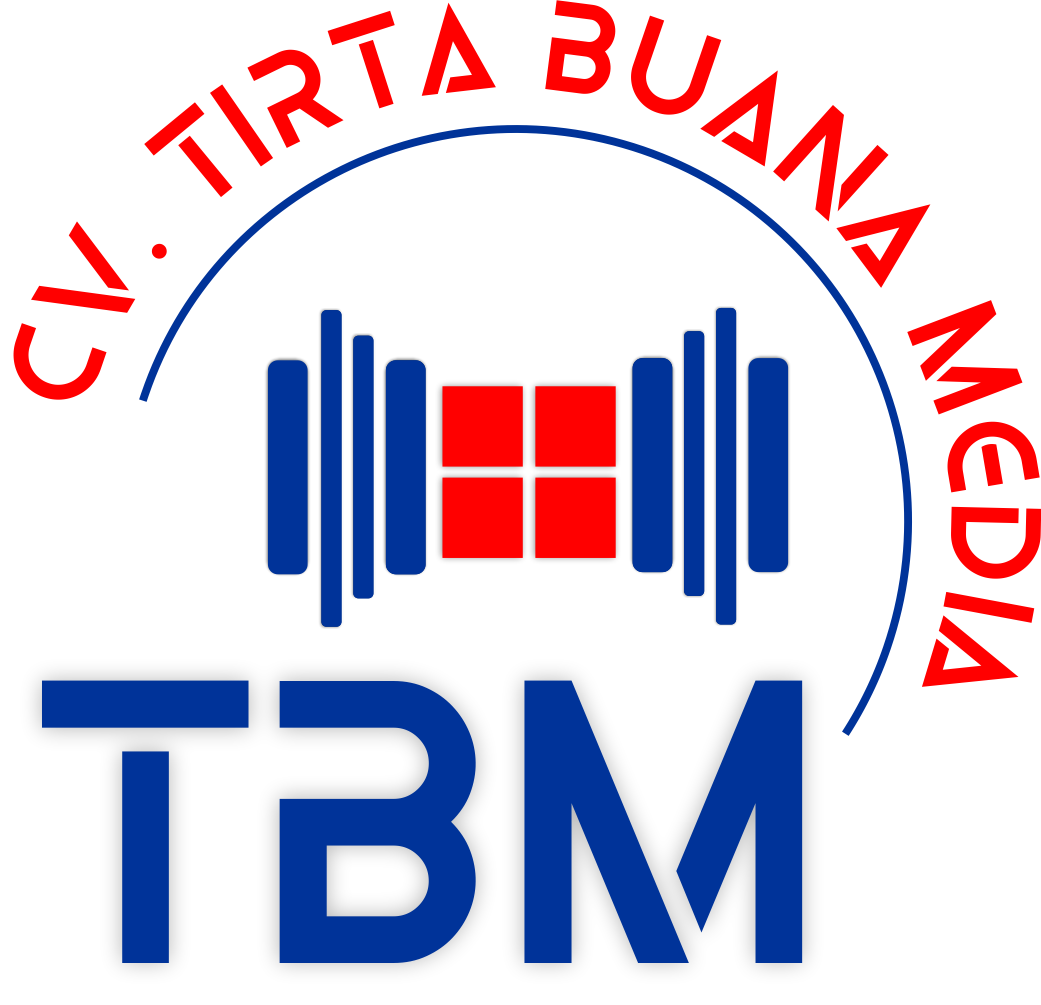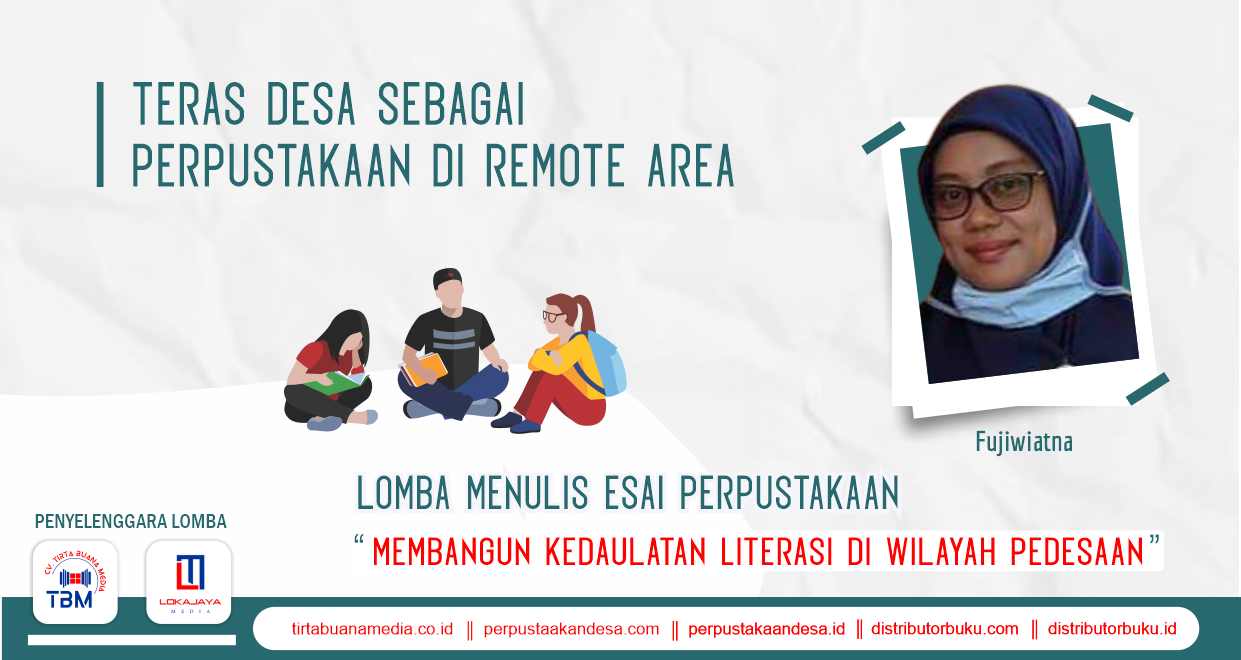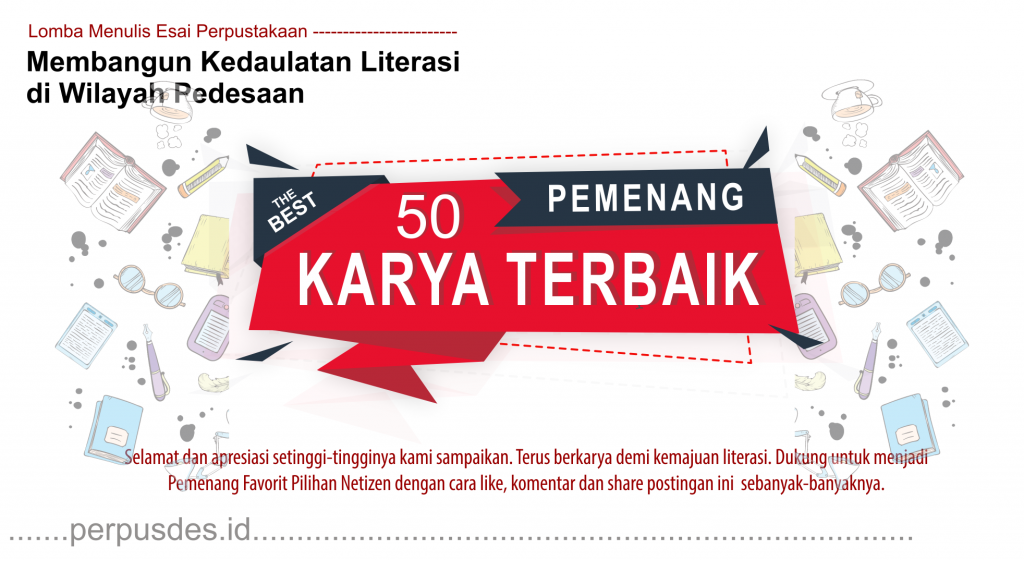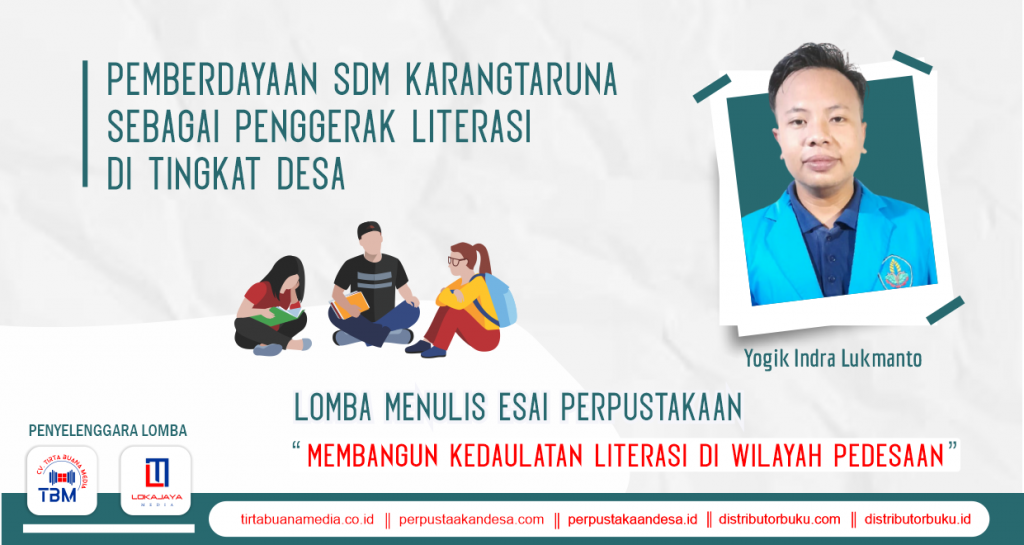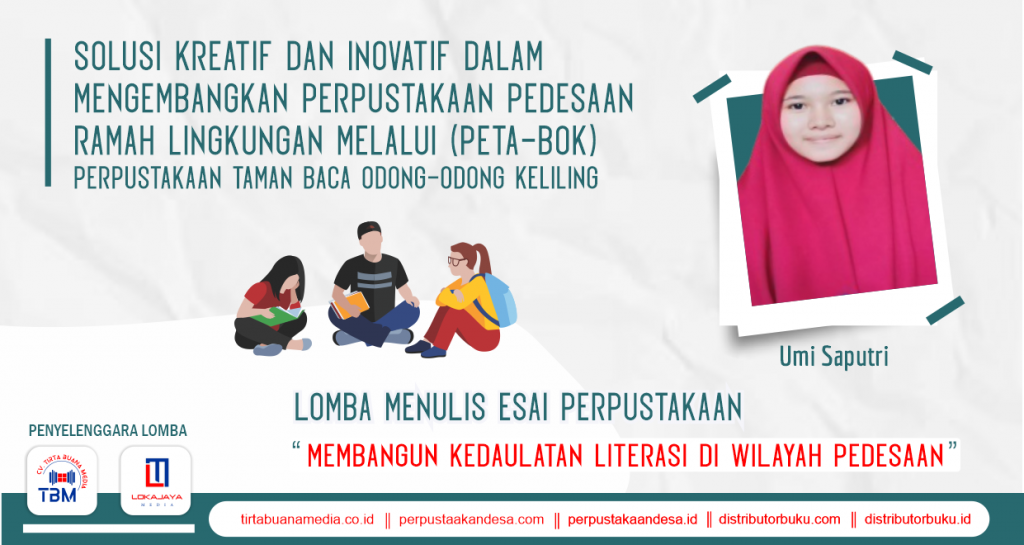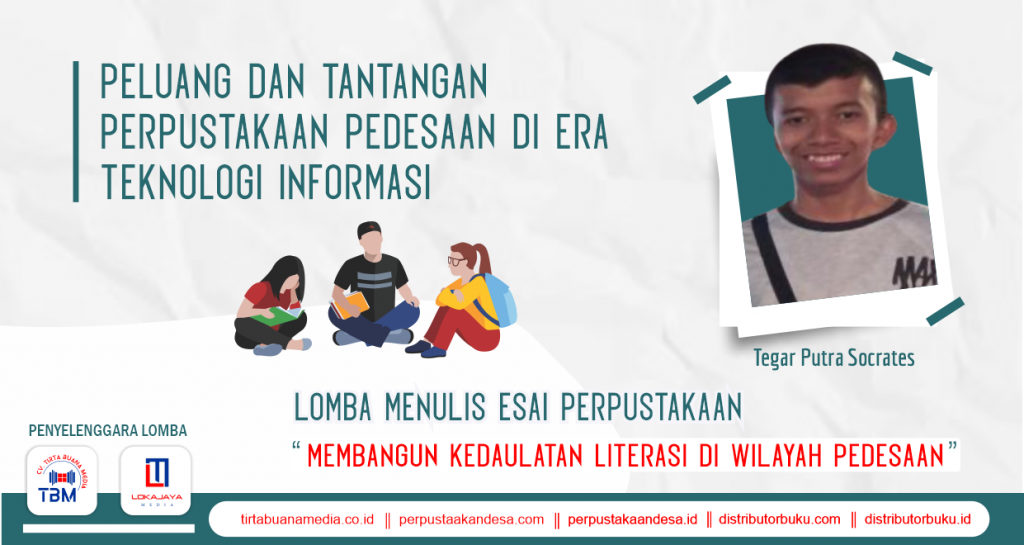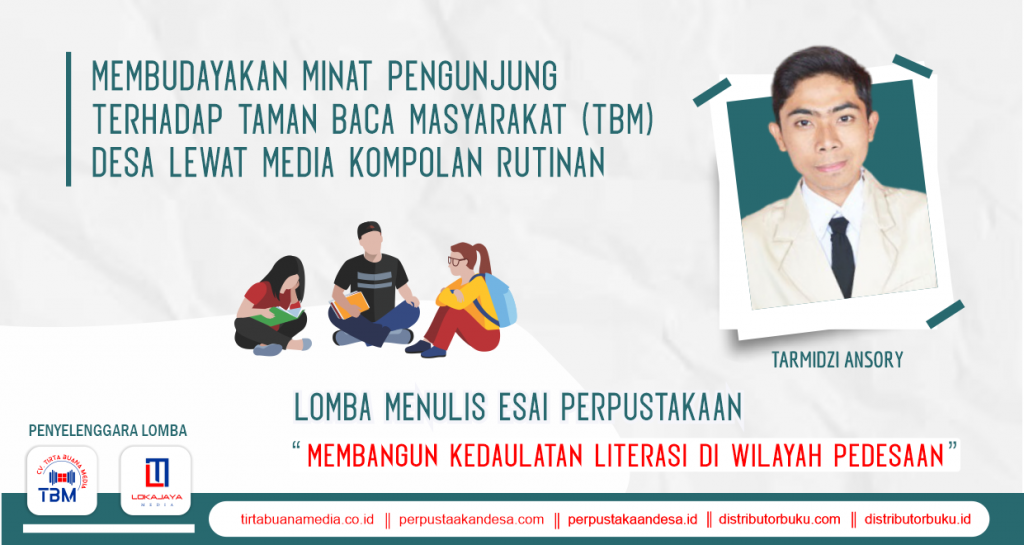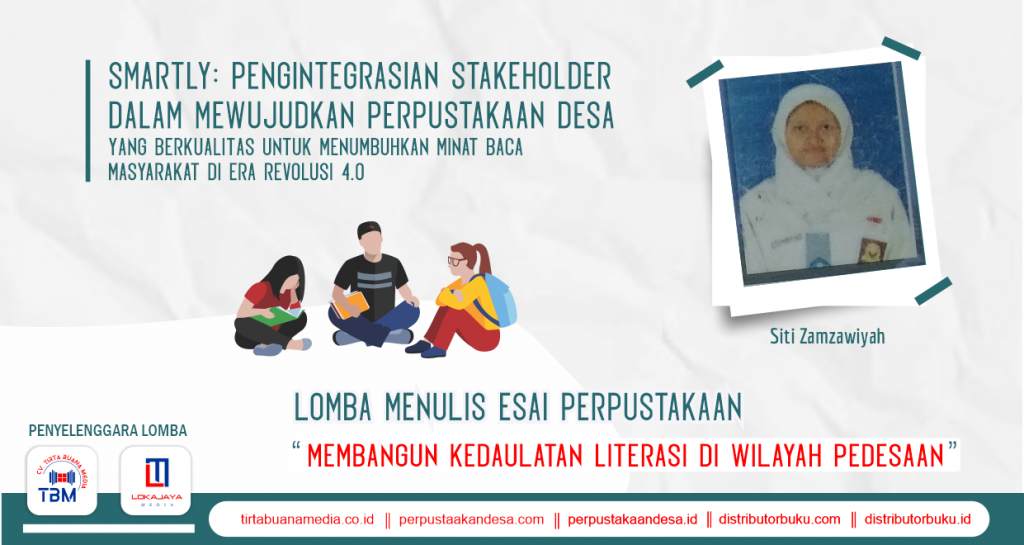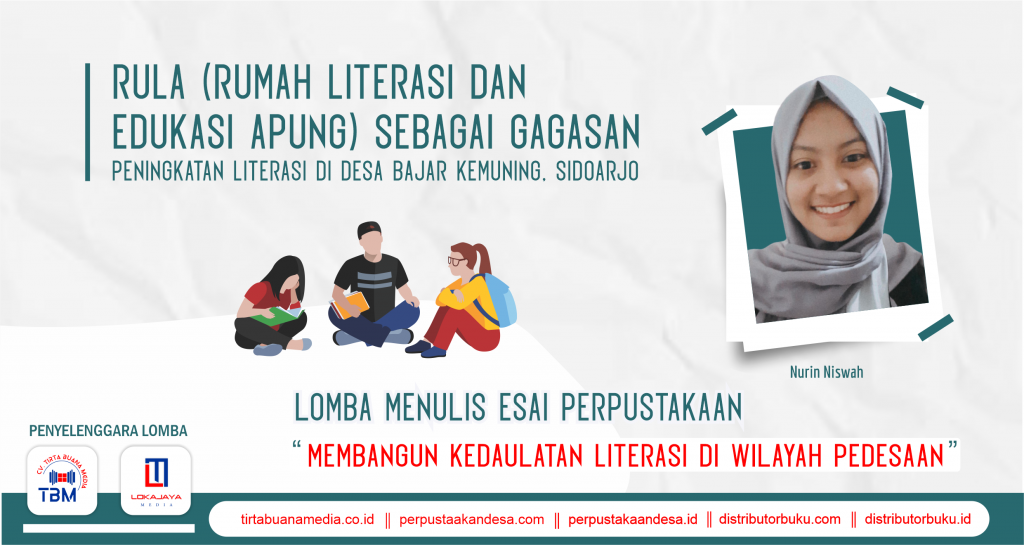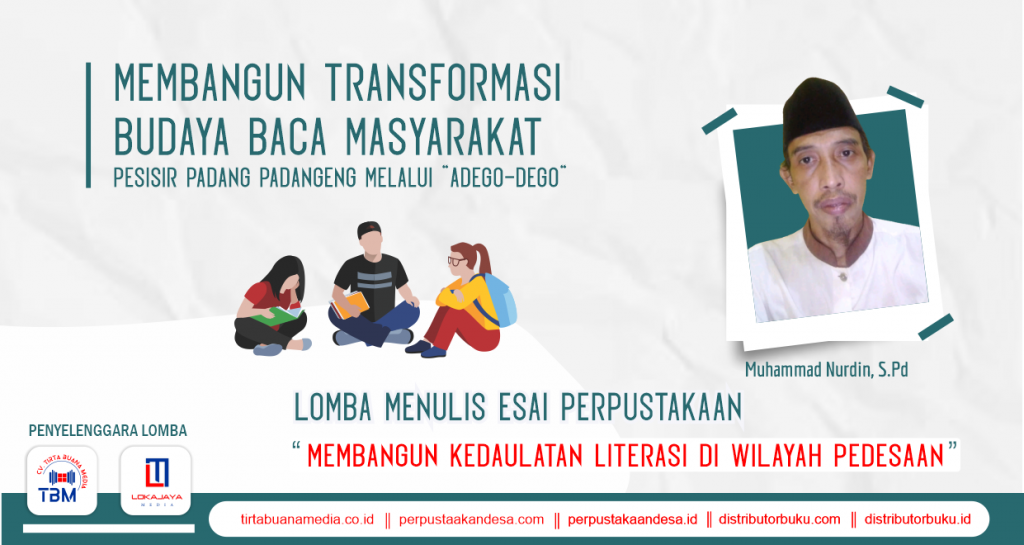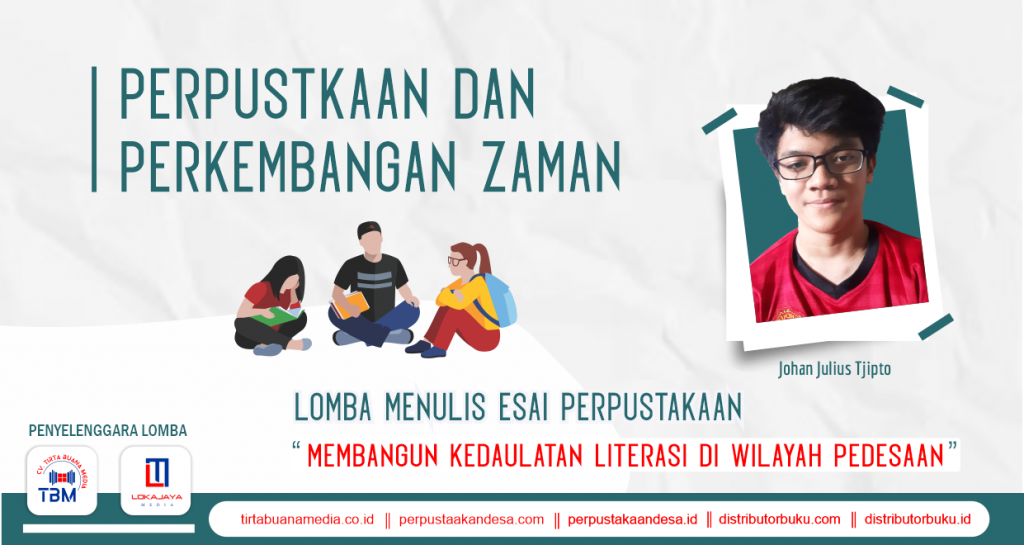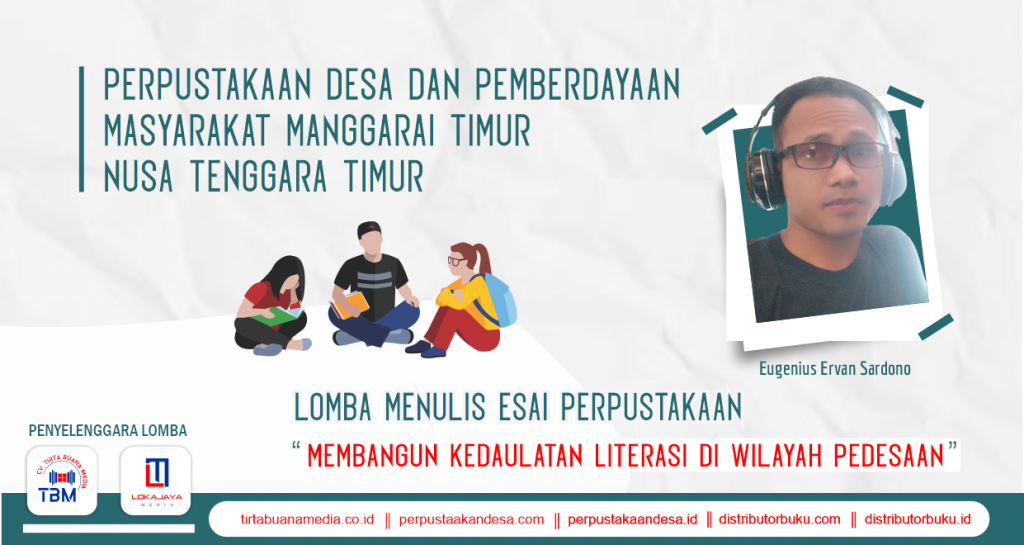Peraturan Kepala Perpustaakn Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
Berdasarkan hal tersebut dana desa yang dikucurkan pemerintah boleh digunakan untuk pembangunan perpusatakaan desa. Namun fakta di lapangan hanya sebagian desa yang memiliki perpustakaan desa. Hal ini disebabkan aparat desa lebih mementingkan sarana seperti transportasi di desa dan fasilitas lain karena ada keraguan untuk membangun perpustakaan.
Pertanyaan pun hadir ketika membahas tentang desa. Apa itu Desa? Apanya yang beda dengan kota?Gaya hidupkah?Orang-orangnyakah?atau karena kota lebih maju? Padahal jika kita amati dan telusuri, hampir sebagian besar masyarakat perkotaan adalah orang-orang yang berasal dari desa. Jika ada seorang pejabat, orang terkenal maka ketika dia sukses selalu membuat aoutobiogarfi atau biografi bangga menjadi anak desa. Buku-buku mereka kemudian tersebar ke berapa perpustakaan. Sekali lagi pada masa yang semakin maju ini desa bukan lagi hal yang sangat primitive, sebagian besar masyarakat desa memiliki keinginan untuk maju. Jadi dimana letak masalahnya? Mari kita bahas sama-sama.
Setiap tahun desa mendapatkan kucuran dana yang sangat besar. Dana tersebut bersumber dari pos APBN, juga mendapatkan alokasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Dana tersebut setiap tahun mengucur sangat deras. Bahkan setiap tahun mendapat dana minimal satu milyar bahkan lebih. Persoalan yang kemudian muncul adalah mampukah aparat desa mengelola dana tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan. Setelah masalah infrastruktur seperti puskesmas, jalan maka pemerintah harus mengalokasikan dana tersebut untuk Sumber Daya Manusia. Terkadang masyarakat menilai hanya membangun sarana saja yang diperuntukkan oleh dana tersebut, padahal membangun sumber daya manusia adalah hal yang jauh lebih penting. Bagaimana perekonomian bisa maju jika sarana tidak mendukung, bagaimana bisa baik? tentunya diharapkan sumber daya manusia yang tangguh dan cerdas, karena meskipun sarana disiapkan tetapi SDM yang buta huruf atau kurang informasi tentu akan menjadi tidak maksimal.
Tantangan terbesar saat ini menghadapi era 4.0-5.0 adalah Sumber daya Manusia (SDM) yang siap berubah dan membuat perubahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi untuk menjadi pengubah atau tren-setter. Perubahan untuk pembangunan desa menjadi kunci utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan budaya literasi untuk anak bangsa yang kebetulan tinggal di pedesaat terkhusus bagi yang tingga di remote area. Mereka adalah milik negara, mempunya hak yang sama dengan perkotaan untuk mendapatkan fasilitas yang memadai.
Untuk megikuti zaman, para aparat desa di tahun 2020/2021 berbondong-bondong memprogramkan wifi atau jaringan masuk kampung dengan berbagai cara. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah para pemuda di desa yang tidak dibekali dengan ilmu yang cukup akhirnya dibutakan oleh dunia maya. Mereka sibuk bermain game, menonton youtube tanpa memikirkan masa depan mereka.Mereka lupa bahwa jika dibekali ilmu yang cukup dari membaca maka para pemuda desa dapat memfilter apa yang mereka lihat di youtube atau media social. Pergaulan mereka pun kadang bercermin dari media social yang mereka lihat.
Namun, sekiranya pemerintah perlahan tapi pasti membuat program untuk pengenalan literasi dengan menjangkau pedesaan terkhusus daerah remote area maka penulis yakin bahwa bangsa akan menjadi makmur dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mencoba memberikan budaya baca melalui teras-teras rumah mereka, maka hal ini akan berdampak positif apalagi buku–buku yang disiapkan mengenai pertanian, agama dan cerita yang mampu membuat mereka terinsiprasi untuk maju.
Remote Area berasal dari kata Bahasa Inggris. Remote yang artinya terpencil. Sementara area artinya daerah. Jadi remote area adalah daerah terpencil. Remote area merupakan suatu tempat atau daerah yang jauh dari pusat peradaban, yang jauh dari teknologi terkini yang diciptakan. Remote area terletak di pelosok pedesaan.
Remote area atau daerah terpencil masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Meskipun ada, tapi sarana dan prasarana itu belum lengkap seperti transportasi, jaringan dan bahan pokok lainnya.
Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa daerah terpencil adalah daerah yang memiliki keterbatasan. Olehnya itu pemerintah harus lebih memperhatikan dan memikirkan cara agar masyarakat di daerah terpencil dapat tersentuh oleh buku bahkan bisa menjadikan bahan bacaan ketika mereka telah bekerja di kebun.
Mengapa dipilih teras? Karena masyarakat pedesaan notabene adalah petani. Mereka jarang menggunakan ruang tamu untuk berkumpul. Mereka menggunakan waktu istirahat mereka di teras sambil bercengkrama dengan tetangga lainnya. Saat mereka bercengkrama pun jelas waktunya, yaitu pada sore hari ketika mereka pulang kebun. Suasana desa yang akrab mampu menjadikan teras rumah menjadi solusi untuk kebersamaan mereka membaca pada sore hari atau ketika malam hari karena jarak rumah satu dengan yang lain masih berdekatan dan tidak dibatasi tembok ataupun pagar. Hal tersebut sungguh jauh berbede dengan perkotaan atau desa di dekat kecamatan. Pemerintah juga harus memperhatikan desa-desa yang jauh dari kecematan yaitu pelosok-pelosok desa yang terpencil.
Masyarakat pedesaan khususnya daerah terpencil (remote area) adalah masyarakat yang butuh perhatian dari semua kalangan terkhusus pemerintah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk setiap desa. Namun pada kenyataannnya hanya sebagian desa yang tersentuh dengan baik alokasi dana tersebut atau mendapatkan pembangunan perpusatakaan. Desa yang dekat dengan kecamataan bisa saja mendapatkan perpusatakaan akan tetapi di daerah terpencil, pemerintah boleh mengecek langsung ke lapangan.
Adanya perpustakaan desa adalah sebuah terobosan yang sangat baik dilakukan pemerintah. Banyak desa yang sudah mendapatkan bantuan perpustakaan desa, namun kita tidak dapat menutup mata bahwa jauh lebih banyak desa yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Pertanyaan yang kemudian menggelitik penulis adalah apakah masyarakat desa yang sudah mendapatkan mendapatkan fasilitas perpusatkaan telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik atau tidak? Sementara notabene masyarakat pedesaan adalah petani. Apakah buku-buku yang telah tersusun rapi di kantor desa telah dikunjungi warga desa atau belum? Apakah perpustakaan tersebut hanya sebatas pajangan bagi para pemeriksa atau inspektorat atau benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Apakah hanya sebagai pelengkap fasilitas di kantor desa saja. Jika ingin mengetahuinya tentunya pemerintah harus terjun langsung ke lapangan dengan jujur memberikan laporan.
Jika dilihat dari fungsi perpustakaan adalah sebagai wadah untuk membaca. Maka perlu ada kreatifitas dari aparat desa agar minat warga masyarakat untuk membaca ada. Apalagi jika melihat rutinitas masyarakat yang pulang kerja hampir semuanya pada sore hari. Pagi sampai siang mereka gunakan untuk bekerja di kebun, sawah, laut dan lain sebagainya. Harus dipahamai bersama bahwa hal yang paling utama dari membaca adalah menumbuhkan kebiasaan membaca dan tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia masih sangat lemah untuk membaca apalagi masyarakat pedesaan.
Berdasarkan hal diatas, penulis memikirkan cara bagaimana agar minat baca para masyarakat bisa ada sehingga mereka tertarik untuk membaca sehingga pengetahuan mereka bertambah. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka Sumber Daya Manusia pasti akan berkualitas dan akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu desa. Sehingga tidak adal lagi berita yang marak beredar tentang pembantu rumah tangga yang buta huruf, ibu yang tidak bisa membaca serta ayah yang tidak lanjut pendidikan.
Fenomena tersebut sungguh miris karena bangsa kita masih sangat rendah kualitasnya terutama di daerah remote area. Sementara era globalisasi mengharapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tanpa kecuali. Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi penonton di negara sendiri. Artinya jangan sampai pasar dikuasai orang asing dan kita tetap menjadi budak. Olehnya itu pemerintah harus menyiapkan secara dini Sumber Daya Manusia yang siap sehingga bangsa Indonesia bisa disegani dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain.
Berdasarkan hal diatas penulis berharap perpustakaan desa tidak hanya menjadi simbol atau pajangan d ikantor desa tetapi benar-benar buku yang ada dimanfaatkan oleh warga desa. Bukan saja desa yang berada dekat dengan kecamatan tetapi desa-desa yang berada di pelosok atau daerah terpencil (Remote Area). Olehnya itu pemerintah khususnya aparat desa lebih fokus untuk meningkatkan minat baca warga desa kemudian menggiringnya untuk masuk ke perpusatakan yang akan atau telah disiapkan di kantor desa jika ada. Bagaimana caranya? Menurut penulis sebaiknya para aparat desa memanfaatkan teras desa atau teras kampung atau teras rumah sebagai perpustakaan mini yang kapan saja warga bisa membacanya sehingga menjadi wahana yang menarik. Jadi sebelum ada perpustakaan di daeran terpencil, pemerintah mulai membangun warga untuk menjadi literat dengan membagikan buku untuk setiap rumah.
Alasan penulis menggunakan teras desa/teras rumah di remote area sebelum memiliki perpustakaan desa adalah sebagai berikut:
- Tingkat pendidikan dan kesehatan sangat rendah
Tingakt pendidikan di desa masih rendah disebabkan karena mereka minim pengetahuan, mereka tidak memikirkan pentingnya pengetahuan. Hal tersebut karena dukungan orang tua sangat kurang seperti dukungan materi, jasmani dan rohani. - Memiliki sarana dan prasarana yang sangat sederhana.
Jika kita mengamati kondisi sekolah yang ada di desa yang sangat memprihatinkan maka tidak heran jiak semangat untuk menuntut ilmu itu kurang.belum lagi jika melihat sarana seperti buku. Guru yang ada di pedesaan pun sangat kurang. - Letak geografis jauh dari perkotaan
Jarak desa dan perkotaan di Indonesia sangat jauh, sehingga akses untuk mendapatkan informasi mengalami kendala. Untuk sampai ke sebuah desa, rata-rata di wilayah Indonesia dijangkau dengan transporasi yang sederhana karena kondisi jalanan yang masih banyak tergolong ekstrem. - Ketergantungan dengan alam tinggi
Sumber daya alam dipedesaan adalah hampir sebagian besar dari bertani atau nelayan sebagai mata pencaharian mereka. - Masyarakat yang terikat tradisi
Masyarakat pedesaan masih banyak yang terkunkung oleh tradisi, sehingga untuk menjadikan perpusatakaan desa sebagai wahana yang diminati itu susah. - Mobilitas sulit terjadi
- Perubahan terjadi sangat lambat
Masyarakat pedesaan sangat lambat menerima perubahan apalagi di daerah remote area, jadi sebaiknya di daerah terpencil terlebih dahulu mengenalkan budaya baca melalui pintu ke pintu serta menjelaskan manfaatnya. Sehingga masyarakat bisa membaca sedikit demi sedikit ketika mereka pulang ke bunn atan nelayan. - Masyarakat tertutup dengan perubahan yang ada.
Masyarakat pedesaan tertutup dengan adanya perubahan karena mereka tidak mendapat akses yang baik untuk mengetahui dunia luar. Jadi program pemerintah untuk membuat perpustakaan desa sangat baik tapi harus perlahan. - Masih kental budaya kebersamaan
Kebersamaan, kekeluargaan masih sangat kental, oleh sebab itu mengharapkan masyarakat datang ke perpustakaan desa suatu hal yang perlu dipikirkan matang-matang agar mereka menyadari pentingnya buku dalam kehidupan mereka. - Masih percaya hal-hal yang gaib
Masyarakat pedesaan masih sangat percaya dengan hal-hal yang gaib. Jadi untuk pengadaan perpustakaan desa harus dilakukan cara yang proaktif agar mereka paham maksud pemerintah. Sehungga perlahan tapi pasi mereka bisa baca dan tulis. - Menggunakan transportasi yang sederhana
Transportasi sederhana dalam kehidupan di pedesaan juga mempengaruhi budaya baca penduduk, hal ini karena masyarakat harus berpikir jarak yang akan ditempuh untuk menjangkau daerah atau tempat perpusatakaan. - Kurangnya alat komunikasi
Alat komunikasi yang kurang juga menyebabkan minat baca masyarakat pedesaan. Namun, jika pemerintah mengoptimalkannya maka warga desa akan mampu mengikuti perkembangan. Tentu saja harus dimulai dari pembiasaan membaca.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya program teras desa atau teras rumah yang dijadikan warga desa untuk menggiatkan budaya baca maka akan menjadi inspirasi pemerintah desa untuk membangun perpustakaan desa khususnya di remote area Sehingga program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud. Program teras desa ataupun teras rumah adlah sebuah inovasi yang sangat tepat digunakan untuk desa terpencil. Hal ini disebabkan letak rumah yang masih tidak dibatasi oleh tembok atau dinding penghalang yang akan membatasi percakapan atau dialog antar sesame warga ketika mereka melepas lelah sambil membaca buku.
Daftar Pustaka:
- https://kbbi.web.id/area.html. 2020
- https://jdih.perpusnas.go.id/detail/89
- Semua/sebagian isi dari tulisan esai ini adalah ide atau pendapat pribadi penulis
BIODATA PENULIS
 Fujiwiatna, lahir di Bule pada tanggal 9 Juli 1979, tepatnya di sebuah desa kecil di Kecamatan Malua yaitu Desa Tallung Tondok, Kab. Enrekang. Penulis dilahirkan dari pasangan H. Achmad Tandingan dan Hj. Hasiah. Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006. Penulis bertugas sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Baraka atau yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 5 Enrekang. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UNM Program Studi Administrasi Pendidikan dengan kekhususan Manajemen Pendidikan.
Fujiwiatna, lahir di Bule pada tanggal 9 Juli 1979, tepatnya di sebuah desa kecil di Kecamatan Malua yaitu Desa Tallung Tondok, Kab. Enrekang. Penulis dilahirkan dari pasangan H. Achmad Tandingan dan Hj. Hasiah. Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006. Penulis bertugas sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Baraka atau yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 5 Enrekang. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UNM Program Studi Administrasi Pendidikan dengan kekhususan Manajemen Pendidikan.
Saat ini penulis dikaruniai seorang putri yaitu Nashwa Almira Hamzah, buah pernikahan dengan Hamzah, S.Ag.,M.Pd. Beliau adalah. seorang tenaga pengajar di MAN Enrekang. Penulis adalah pembina KIR, Debat Bahasa Indonesia dan pembina Bengkel Seni & Sastra di SMA Negeri 5 Enrekang. Penulis adalah instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten Enrekang sejak tahun 2016-2018 dan tahun 2019 berhasil menyumbangkan medali Perak untuk Kabupaten Enrekang pada lomba Kreativitas Guru (Penulisan Esai) pada HUT PGRI Tingkat Provinsi. Buku ini adalah buku tunggal pertama penulis. Penulis dapat dihubungi di nomor telepon 085314965591 dan email: [email protected].