Indonesia merupakan salah satu negara di Dunia yang memiliki beragam budaya yang unik. Keberagaman menjadi keunggulan tersendiri bagi suatu negara, baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dari keberagaman yang unik inilah yang kemudian muncul bahasa-bahasa yang mencerminkan suatu daerah misalnya Kabupaten Timor Tengah Utara identik dengan bahasa dawan, Kabupaten Malaka bahasa Tetun, dan Kabupaten Belu identik bahasa, Tetun, Marae, dan Kemak. Namun, keberagaman bahasa ini dapat di satukan melalui satu bahasa yaitu Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyusun dan mengungkapkan kembali hal-hal yang ada disekitarnya kepada manusia lain sebagai bahan komunikasi. Berbahasa merupakan tindak menyampaikan dan mentransfer pesan antar personal dalam konteks tertentu. Melalui bahasa, penutur melakukan tindak menyampaikan pesan agar dipahami mitra tutur sesuai dengan gagasan yang ada dalam pikirannya (Sumarti, 2017). Bahasa terbagi menjadi dua, yakni bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan sebagai bahasa primer, sedangkan bahasa tulis sebagai bahasa sekunder (Mohamad, 2010).
Berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia, maka akan sangat erat pula hubungannya dengan literasi. Literasi berarti kemampuan membaca dan menulis atau juga disebut dengan melek aksara (Heru Susanto, 2016). Literasi juga diartikan sebagai sebuah pendidikan atau pembelajaran (Muhammad Muiz, n.d.). Adapun menurut KBBI V, literasi memiliki beberapa pengertian antara lain; (1) Kemampuan menulis dan membaca; (2) Pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; (3) Kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan dalam hidupnya.
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa respon masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan masih lamban. Hal ini dapat diatasi dengan gerakan-gerakan literasi melalui membaca dan menulis. Membaca dan menulis dapat ditingkatkan melalui perpustakaan desa atau dengan mengadakan taman baca di Desa. Kepala Biro Komunikasi Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Asianto Sinambela (dalam berita pojok, 2016). Bukti bahwa minat baca yang masih memprihatinkan pada bangsa Indonesia juga terlihat berdasarkan survey UNESCO. Minat baca bangsa Indonesia baru mencapai 0,001 persen. Hal ini berarti jika diibaratkan seperti hanya ada satu masyarakat yang membaca dari seribu masyarakat yang menduduki Indonesia (Berita Pojok, 2016).
Pada tahun 2018 di Indonesia telah berdiri 83 Kampung Literasi (KL). Sementara untuk TBM, ada sekitar 7.028 yang tersebar di seluruh pulau (Very, 2018). Untuk wilayah Malang dan Batu, sedikitnya terdapat di 25 lokasi di Kota Malang, 13 lokasi di Kota Batu dan 87 unit TBM di Kabupaten Malang (Izzah, 2018). Keadaan tersebut akan membantu pembangunan nasional demi kemajuan daerah. Hal itu juga tidak akan terlepas dari peran anak muda.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan adanya pelayanan kepemudaan berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda. Pasal 24 menyebutkan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan merupakan aktor-aktor yang memiliki kewajiban memfasilitasi pemuda. Peran sektor swasta dan akademisi dalam pemberdayaan pemuda juga sangat dibutuhkan.
Literasi sebagai Praktik Sosial
Dalam beberapa dekade terakhir, istilah literasi (literacy) tampak begitu populer. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Latin yakni literatus yang berarti a learned person (orang yang belajar) atau littera (huruf) yang artinya melibatkan penguasaan berbagai sistem tulisan serta konvensi yang menyertai. Pada hakikatnya, konsepsi literasi terus mengalami elaborasi, sehingga tidak hanya berhubungan dengan keaksaraan dan bahasa, tetapi sudah merambah pada fungsi keterampilan hidup (life skills) bahkan literasi moral (moral literacy).
Konsep literasi sebagai memahami dan memahamkan melahirkan istilah literasi produktif dan literasi-reseptif. Konsep ini merujuk pada upaya memahami melalui aktivitas berbahasa pasif (membaca, menyimak), dan upaya memahamkan melalui aktivitas berbahasa aktif (menulis, berbicara). Dengan demikian literasi produktif dibatasi maknanya sebagai proses transfer informasi melaui keterampilam menulis yang mampu memahamkan melalui pemanfaatan teknologi (Agustin, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah literasi berasal dari kata literer yang berkaitan dengan tradisi tulis. Berbagai penelitian yang memandang literasi sebagai praktik sosial termasuk dalam bidang kajian baru yang disebut New Literacy Studies (NLS).
Dalam sebuah laporan UNESCO, Bulgaria, Kolombia, dan Meksiko misalnya, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis teks kalimat sederhana. Sementara Ukraina, Malaysia, dan Hungaria mengaitkan literasi dengan tingkat pendidikan. Ada juga negara-negara yang membangun pengertian literasi secara lebih spesifik. Cina misalnya, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti minimum 2.000 aksara Cina di wilayah perkotaan dan 1.500 karakter di wilayah perdesaan. Dalam konteks tersebut, maka menjadi hal yang wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dua tahun lalu menyumbangkan sedikitnya 2.500 buku yang terdiri dari 167 judul buku tentang anti korupsi ke Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai salah satu upaya pengenalan anti korupsi lewat literasi (Rifa’i, 2017).
Walaupun negara maju seperti Singapura masih mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami bacaan dalam bahasa yang spesifik (Efendi, 2017). Beberapa konsep yang sering digunakan antara lain literacy event (peristiwa literasi) dan literacy practices (praktik literasi). (Dewayani Sofie, 2017) dengan mengutip Shirley Heath (1983) bahwa dalam kajian tentang literasi di dalam tiga komunitas negara bagian South Carolina telah mendefinisikan peristiwa literasi sebagai apapun dimana sebuah bentuk tulisan atau teks menjadi bagian dari interaksi para partisipan dan proses pemaknaan teks tersebut.
Secara sederhana, istilah peristiwa literasi bisa dimaknai sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dan di dalamnya terlahir produk tertulis. Sementara itu, praktik literasi tidak hanya mencakup peristiwa yang bisa dilihat tersebut, namun juga nilai-nilai dan perilaku dari orang-orang yang terlibat dalam praktik literasi tersebut.
Secara ontologis konsep literasi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yakni: (1) Literasi dasar (basic literacy) berhubungan dengan kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis dan berhitung; (2) Literasi Perpustakaan (Library Literacy) yang terkait dengan penyampaian pemahaman untuk membedakan bahan bacaan yang bersifat fiksi dan nonfiksi, untuk memahami pemanfaatan katalog serta aplikasi kodifikasi koleksi; (3) Literasi Media (Media Literacy) yang berhubungan dengan pemahaman subtansi sampai framing media massa; (4) Literasi Teknologi (Technology Literacy) yang berhubungan dengan kemampuan memahami eksistensi dan nilai kemanfaatan perangkat teknologi; serta (4) Literasi Visual (Visual Literacy) yang berhubungan dengan pemahaman lanjutan antara unsur literasi media dan literasi teknologi.
Persepektif ontologis tersebut, terlihat bahwa tafsir bahkan makna operasional literasi telah mengalami perkembangan sangat signifikan. Literasi tidak berhenti hanya pada kegiatan calistung yang membosankan untuk beberapa orang, tetapi telah berkembang menjadi pemahaman yang lebih kontekstual. Mulai yang terkait dengan kegiatan pencerdasan sisi kognitif (common sense), pencerahan sisi afektif (rasa) serta dapat direfleksikan dalam tindakan emprik (psikomotorik). Walaupun, membaca merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar (Faradina, 2017). Maka, aktivitas literasi yang kalah masif jika dibandingkan dengan adopsi teknologi, membuat kehidupan manusia penuh dengan masalah (trouble maker).
Kemampuan literasi yang rendah tentunya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi menimbulkan dan memperkeruh konflik yang terjadi di masyarakat. Contoh yang paling nyata tampak dari begitu mudahnya sebagian masyarakat menyebarkan informasi tanpa berfikir kritis dan melakukan pengecekan sumber darimana dan untuk apa informasi itu muncul. Fenomena banyak bersebarannya informasi yang ada di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir adalah gambaran singkat efek dari lemahnya kemampuan literasi sebagian besar masyarakat (Agustino, 2018).
Nilai-nilai kesukarelawanan (volutarism) menjadi kunci kekuatan gerakan literasi berbasis komunitas. Sebagaimana hasil penelitian (Yanto, 2016) bahwa aktivitas gerakan literasi sangat bergantung pada aktivitas yang dibuat oleh Sudut Baca Soreang (SBS) dengan dukungan relawan yang ada. Seluruh kegiatan SBS telah tersusun dan terencana mulai dari kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan dengan sasaran pemuda, pelajar, perempuan dan UMKM. Hal tersebut tentu berbeda motif dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis isu-isu yang lebih bersifat profit oriented seperti pariwisata. Karena target utama yang ingin dicapai hanya semata-mata peningkatan pendapatan (Harun, 2014). Walaupun, proses pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata sebagai salah satu contoh, tetap melibatkan peran aktif masyarakat sebagaimana yang berbasis pada gerakan literasi, mulai dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian agar tetap menghormati nilai-nilai sosial dan keagamaan di sekitar kawasan wisata (Ridlwan, 2017).
Berdasarkan hasil penelitian (Agustino, 2019) tentang “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara” menunjukan bahwa yang melatarbelakangi serta fokus pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi yang dilakukan di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara adalah sebagai berikut: (1) Eksistensi pemberdayaan berbasis gerakan literasi di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara sebagai jawaban atas problematika sosial-historis wilayah desa; (2) Realisasi pemberdayaan di laksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan (voluntarism) dan kemandirian (independence); (3) Fokus utama dari kegiatan pemberdayaan adalah transformasi nilai-nilai karakter (character building) utamanya bagi kelompok usia produktif serta mendorong kemandirian sosialekonomi berbasis pada rangkaian kegiatan soft skill tematik.
Gerakan literasi memang seharusnya dilakukan dan didukung oleh berbagai pihak. Fauzan (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat memengaruhi minat pembaca, kaitannya dalam memediasi atau pun memfasilitasinya. Menurutnya, dalam proses penciptaan literasi, peran mahasiswa dalam lingkungan sosial mempunyai fungsi sebagai pendukung yang sangat signifikan karena seorang mahasiswa diasumsikan memiliki tingkat kemauan literasi yang lebih baik. Maka dari itu, peran lingkungan sosial khusunya kaum milenial yang berpendidikan tinggi (mahasiswa) menjadi bidikan utama dalam pengimplementasian gerakan literasi (Achmad, 2018).
Pemuda sebagai Penggerak Literasi Digital di Wilayah Pedesaan
Misi Program Sipkades adalah memberdayakan pemuda dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membangun desa. Pemuda era ini adalah digital natives, yakni generasi yang lahir setelah tahun 1980an. Generasi ini telah tumbuh dalam lingkungan digital (Lisa, 2015) Pemuda membangun desa menjadi energi baru bagi pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagai nilai positif karena Indonesia memiliki jumlah usia produktif yang memadai. Untuk itu, perlu ada upaya serius dari berbagai kalangan untuk menyadarkan pemuda di desa sebagai agen perubahan sosial.
Pemuda sebagai agen perubahan harus diarahkan kepada orientasi penguatan sumber daya manusia. Orientasi ini sebagai konsekuensi logis karena tantangan kehidupan di era global semakin tidak menentu. Tantangan era global yang paling menonjol adalah era disrupsi. Era ini sebagai akibat langsung dari pengaruh revolusi industri 4.0. Hasil revolusi ini kerap disebut dengan era digital (Bashori, 2018).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu faktor pendorong inisiasi Sipkades. UU Desa membuka peluang yang luas bagi desa untuk mengelola potensinya. Pasal 3 mengemukakan 13 asas pengaturan desa, yakni rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaa, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Semua asas tersebut masuk dalam cakupan pemberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan. Upaya mewujudkan agenda tersebut masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 68 ayat 2 menyatakan bahwa salah satu kewajiban masyarakat desa adalah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
Gerakan literasi digital dihubungkan dengan teknologi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran anak muda dalam mengolah teknologi. Saat ini teknologi dapat dimanfaatkan dalam mendukung aktivitas manusia. Prinsipnya teknologi dapat menguasai manusia. Hal ini dapat akhiri dengan menyediakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini sejan dengan kata-kata Bung Karno “Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia”. Kata-kata tersebut menunjukan bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, maka anak-anak mudalah yang akan menjadi motor penggerak demi kemajuan bangsa. Anak-anak muda menjadi andalan bangsa. Anak-anak muda menjadi kekuatan bangsa, anak-anak muda menjadi benteng bangsa.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pada usia tersebut manusia berada pada masa produktif dan memiliki energi besar, atau sering disebut di negara barat sebagai masa younge, wild, and free. Ibarat dua sisi mata pisau, usia muda sangat rentan terhadap kegiatan positif maupun negatif. Baik positif maupun negatif, kondisi pemuda dapat menjadi modal penting untuk dijadikan agen perubahan sosial. Dengan catatan, program pemuda harus berbasis needs oriented. Menurut data BPS, pada tahun 2016 jumlah pemuda di Indonesia mencapai 62.061.400 jiwa.
Berdasarkan hasil survei (Yasraf A, 2012) penggunaan TIK tahun 2017, 45 persen penduduk Indonesia menggunakan internet. Besaran ini meliputi 61,83 persen penduduk urban dan 32,50 persen penduduk rural. Sedangkan (APJII, 2019) dilihat dari jenis kelamin, 45,84 persen penduduk laki-laki dan 44,24 persen penduduk perempuan. Pengguna internet ini didominasi oleh penduduk usia produktif berusia 20-29 tahun sebesar 60,15 persen. Sisanya 50,45 persen penduduk usia 30-49 tahun, 43,90 persen penduduk usia 9-19 tahun, dan 26,02 persen penduduk usia 50-65 tahun. Sementara itu, jika dilihat dari jenjang pendidikan, penduduk dengan jenjang pendidikan S2/S3 menduduki persentasi tertinggi sebagai pengguna internet, yakni 87,50 persen. Diikuti jenjang pendidikan Diploma/S1 sebesar 83,97 persen, jenjang pendidikan SMA 61,64 persen, jenjang pendidikan SMP 35,53 persen, jenjang pendidikan SD 9,82 persen dan penduduk tidak sekolah 6,73 persen.
Pemuda (Mahasiswa) adalah kaum akademis dan sebagai agen perubahan. Mahasiswa juga disebut sebagai motor penggerak kemajuan negara. Sebagai mahasiswa jangan mati dalam kaca perkuliahan yang hanya mampu menerima teori namun, sulit untuk menerapkan. Mahasiswa harus mampu berkontibusi bagi daerah dalam mendukung kemajuan daerahnya. Mahasiswa adalah mesin penggerak utama gerakan literasi khususnya pada pedesaan. Mengapa demikian? Karena mahasiswa memeliki kemampuan yang lebih dari masyarakat di desa sehingga mahasiswa mampu berperan aktif dalam mendukung kememajukan suatu desa/daerah. Selain itu mahasiswa disebut sebagai pelengkap masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa harus bergerak, cepat, tepat, dan eksekusi.
Bagi sebagian orang -terutama akademisi perpustakaan merupakan satu hal yang tidak asing. Perpustakaan dapat kita temukan di setiap negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa. Secara umum perpustakaan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Lembaga Keagamaan, Perpustakaan Internasional, Perpustakaan Kantor Perwakilan Negara-negara Asing, Perpustakaan Pribadi, dan Perpustakaan Digital (Sutarno, 2006). Setiap perpustakaan tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama yaitu menghimpun, memelihara, dan memberdayakan koleksi yang dimilikinya. Selanjutnya fungsi spesifik perpustakaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 3. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Perpustakaan desa memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat desa. Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Kedudukan dan peranan ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki beragam peranan sebagai hasil dari pergaulan dalam hidupnya. Peranan akan mengatur individu dalam berperilaku. Hubungan sosial adalah hubungan antar peranan-peranan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Kehadiran perpustakaan desa pada dasarnya milik, dibangun oleh rakyat dan ditujukan untuk melayani masyarakat yang bersangkutan. Perpustakaan desa mempunyai peran yang strategis bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman (Sutarno NS, 2008).
Daftar Pustaka
- Agustin, Sri, Bambang Eko Hari Cahyono. (2017). “Gerakan Literasi Sekolah Untuk Meningkatkan Budaya Baca Di SMA Negeri 1 Geger.” Linguista Vol. 1 (2): 55–62. http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/linguista.
- Agustino, Hutri. (2018). Strategi Gerakan Literasi Di Era Globalisasi (Malang Post).
- Agustino Hutri, 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara. Jurnal Sospol, Vol 5 No 1 (Januari-Juni 2019), Hlm 142-164.
- Achmad Uzair Fauzan. (2018). MORALITAS, PASAR, DAN GERAKAN DAKWAH: Dinamika Literasi Generasi Milenial di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Retrieved from http://ejournal.uinsuka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif /article/view/131-11.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018” (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019); Peneliti, “Survey Penggunaan TIK 2017 Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat”.
- Berita Pojok. (2016). N. Retrieved from htttp://gobekasi.pojoksatu.id/2016/05 /19/survei-unesco-minat-bacamasyarakat-indonesia-0001-persen/
- Dewayani, Sofie, Pratiwi Retnaningdyah. (2017). Suara Dari Marjin: Literasi Sebagai
- Praktik Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Efendi, David. (2017). “Mencari Model Gerakan Literasi Masyarakat.” https://www.researchgate.net/publication/320627639_Mencari_Model_Gerakan_Literasi_Masyarakat_1.
- Faradina, Nindya. (2017). “Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah Terhadap
- Minat Baca Siswa Di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah
- Jatinom Klaten.” Jurnal Hanata Widya 6 (8).
- Harun, Zulkarnain. (2014). “Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
- Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Komunitas Lokal: Kasus Di
- Kota Padang Panjang.” JANTRO 16 (1).
- http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view
/15. - Heru Susanto. (2016). Membangun Budaya Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Menghadapi Era Mea. Singkawang: STKIP Singkawang. Retrieved from ttp://journal.stkipsingkawang.ac.id/in dex.php/JP-BSI/article/view/70/pdf
- Izzah, Imarotul. (2018). Jumlah TBM Terus Berlipat. https://redarmalang.id/jumlah-tbm-terus-berlipat/.
- Khoiruddin Bashori, “Pendidikan Politik di Era Disrupsi,” Sukma: Jurnal Pendidikan 2, no. 2
- Lisa Lindawati, “Pola Akses Berita Online Kaum Muda,” Jurnal Studi Pemuda 4, no. 1 (2015):
- Mohamad Jazeri. (2010). Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah. Tulungagung: Cahaya Abadi.
- Ridlwan, Muhammad Ama, Dkk. (2017). “No Title.” 2 (2): 141–58. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/9933/6420. Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifa’i, Bahtiar. (2017). “Dukung Literasi Antikorupsi, KPK Sumbang 2.500 Buku Ke
- TBM Di Serang.” https://news.detik.com/berita/d-3482101/dukungliterasi-antikorupi-kpk-sumbang-2500-buku-ke-tbm-di-serang.
- Sumarti, E. (2017). GANGGUAN KOMUNIKATIF DALAM TUTURAN LISAN ANAK AUTIS.
- LITERA, 16(2), 282–294.
- Sutarno NS. 2008. Membina Perpustakaan Desa. Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu faktor pendorong inisiasi Sipkades.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu faktor pendorong inisiasi Sipkades.
- Very. (2018). “Gerakan Literasi Mencegah Bahaya Radikalisme.” http://indonews.id/artikel/13502/Gerakan-Literasi-Mencegah-BahayaRadikalisme/.
- Yanto, Andri, Dkk. (2016). “Model Aktivitas Gerakan Literasi Berbasis Komunitas
- Di Sudut Baca Soreang. Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan.” 2
- Yasraf Amir Piliang, “Mayarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial’, Jurnal Sosioteknologi 27, no.11 (2012): 143–56.
Biografi Penulis
 Saya Lambertus Nesi Bria. Lahir di Manufui pada tanggga 12 November 1998 yang tepatnya di Desa Upfaon Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. saya adalah anak ke-dua dari 5 bersaudara. Saya pernah menempuh pendidikan di SDK Manufui 1 pada tahun 2005, dan tamat pada tahun 2012. Setelah itu saya melanjutkan ke sekolah menengah di SMP Mimbar Budi Manufui pada tahun 2012, dan tamat pada tahun 2015. Saya juga melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Bina Karya Atambua pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Setelah itu saya melanjutkan sekolah saya ke perguruan tinggi Universitas Timor (UNIMOR). Di Universitas Timor saya mengambil jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, dan sekarang sudah semester 6.
Saya Lambertus Nesi Bria. Lahir di Manufui pada tanggga 12 November 1998 yang tepatnya di Desa Upfaon Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. saya adalah anak ke-dua dari 5 bersaudara. Saya pernah menempuh pendidikan di SDK Manufui 1 pada tahun 2005, dan tamat pada tahun 2012. Setelah itu saya melanjutkan ke sekolah menengah di SMP Mimbar Budi Manufui pada tahun 2012, dan tamat pada tahun 2015. Saya juga melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Bina Karya Atambua pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Setelah itu saya melanjutkan sekolah saya ke perguruan tinggi Universitas Timor (UNIMOR). Di Universitas Timor saya mengambil jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, dan sekarang sudah semester 6.
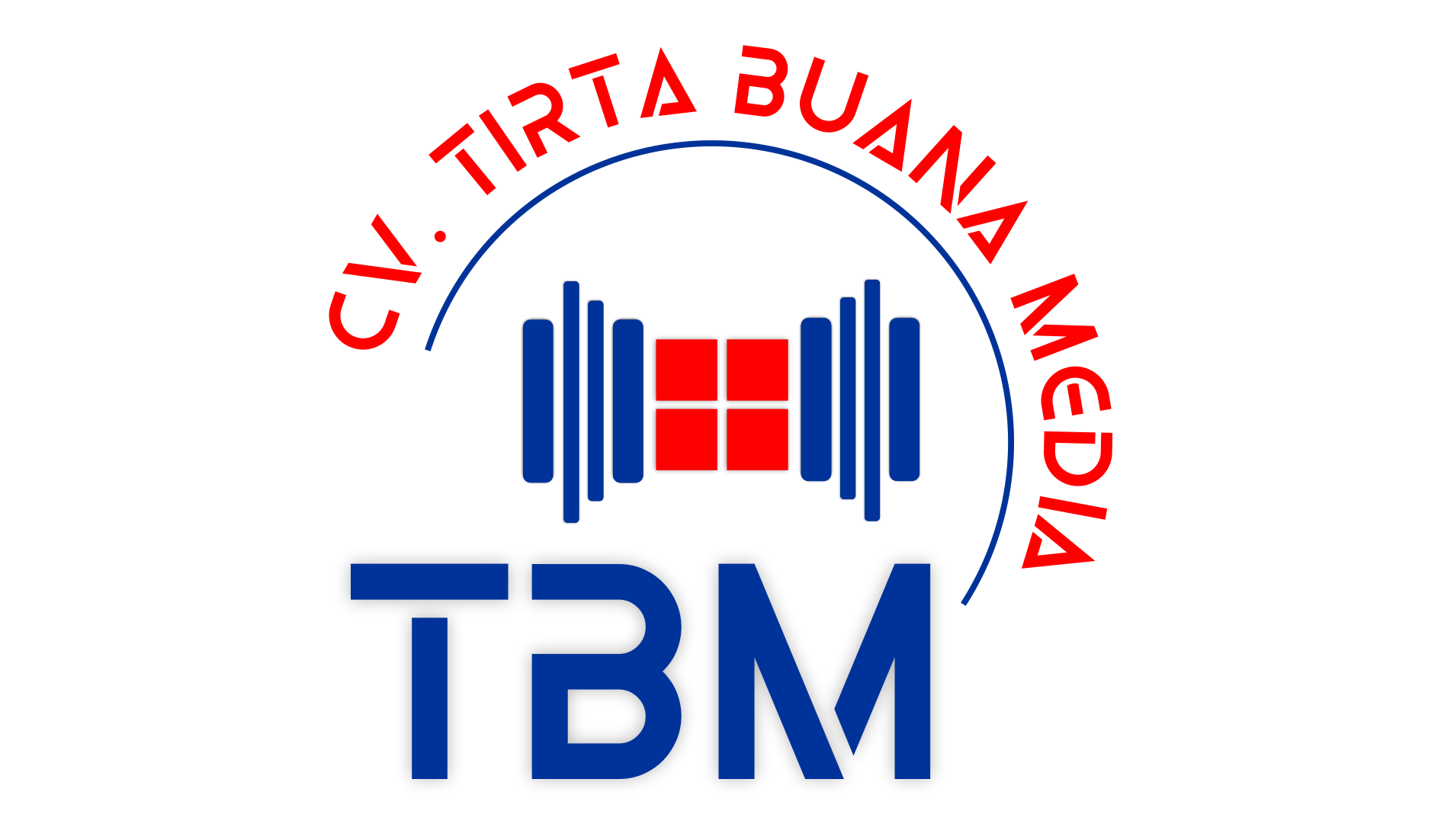
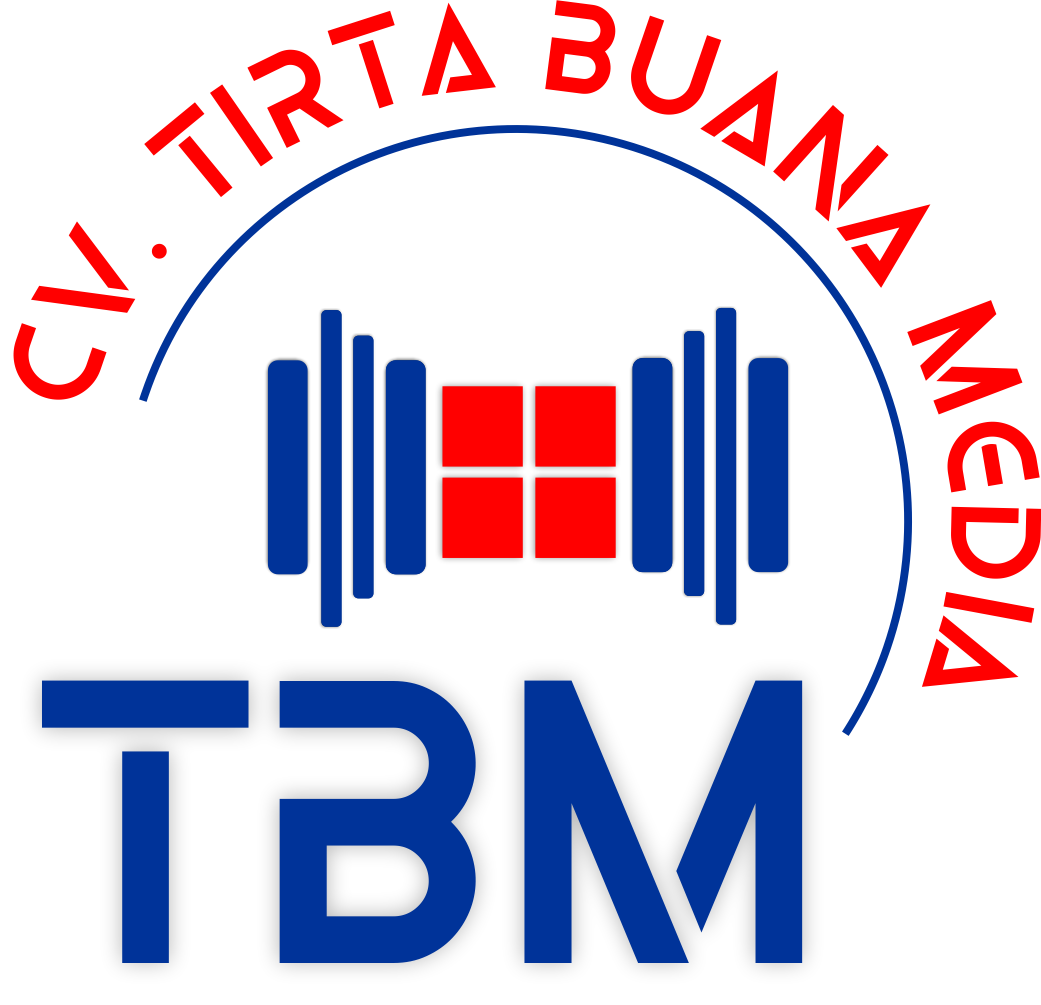
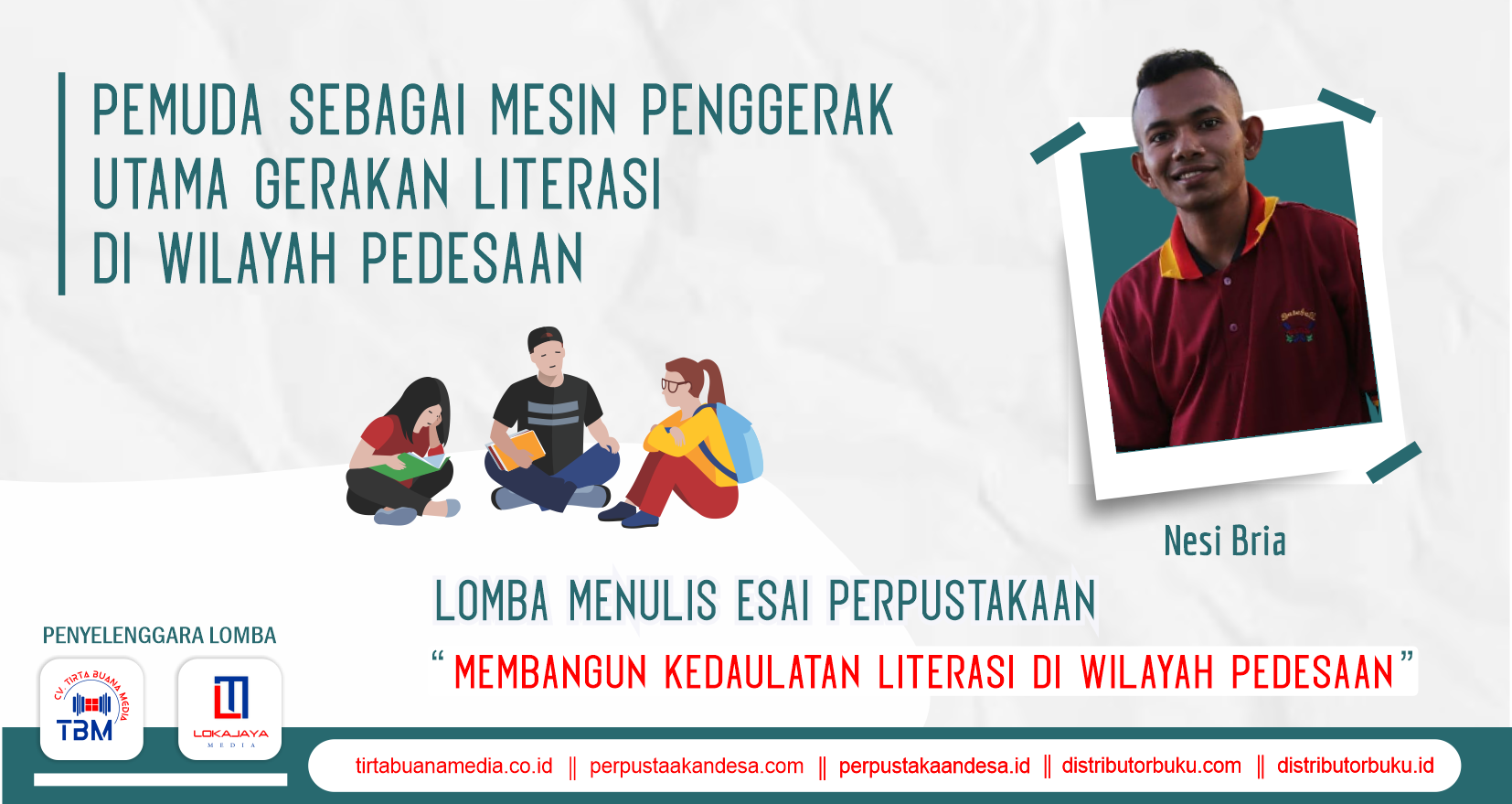

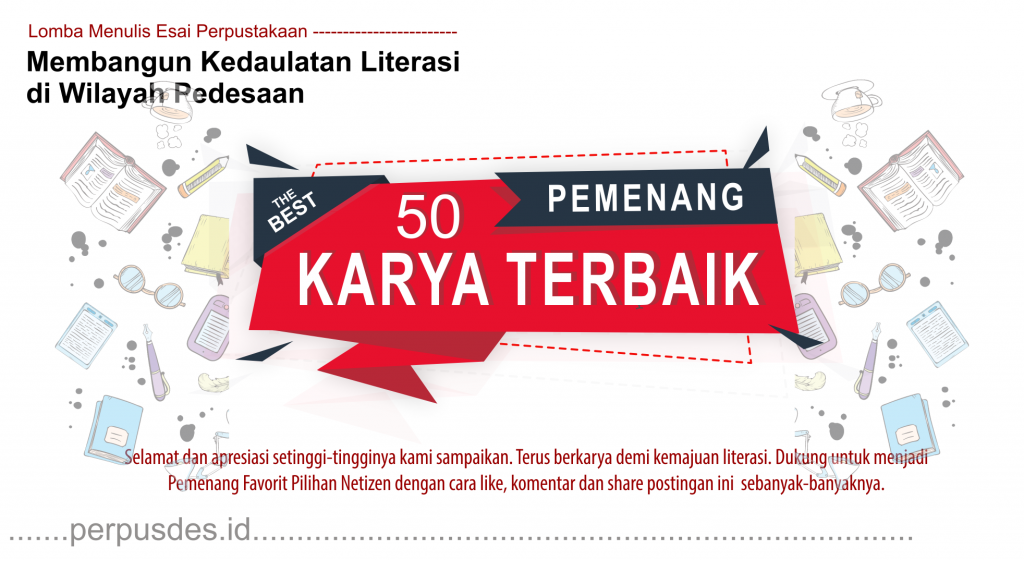
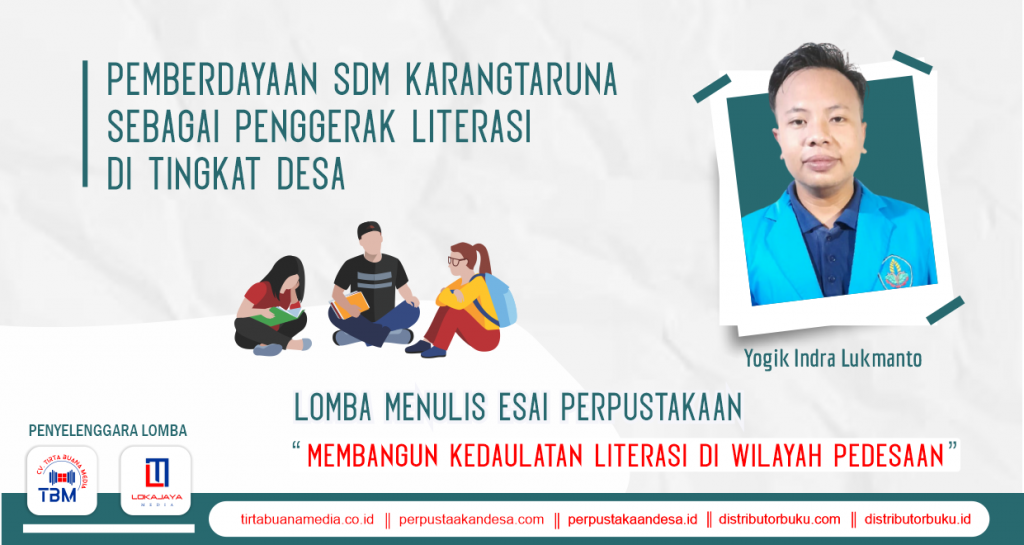
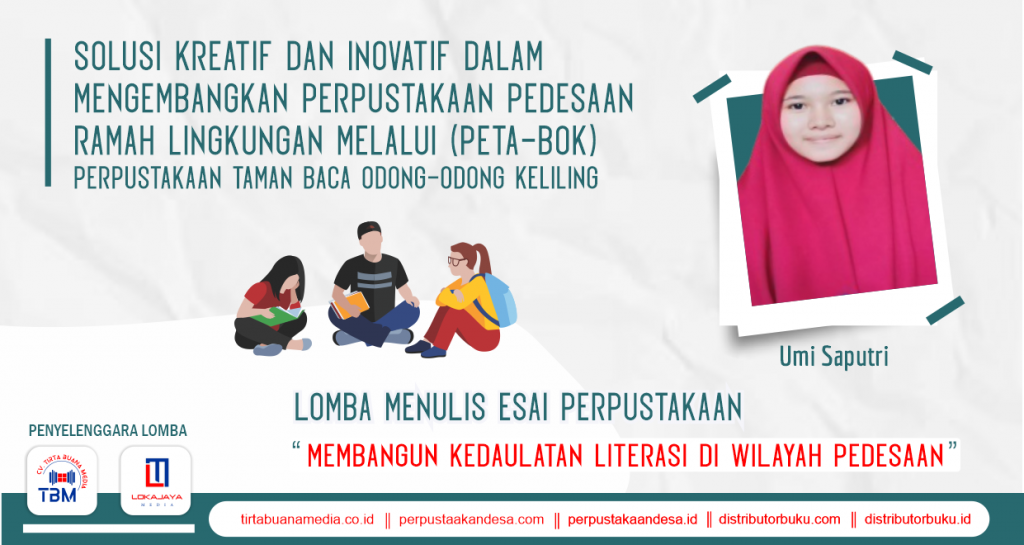
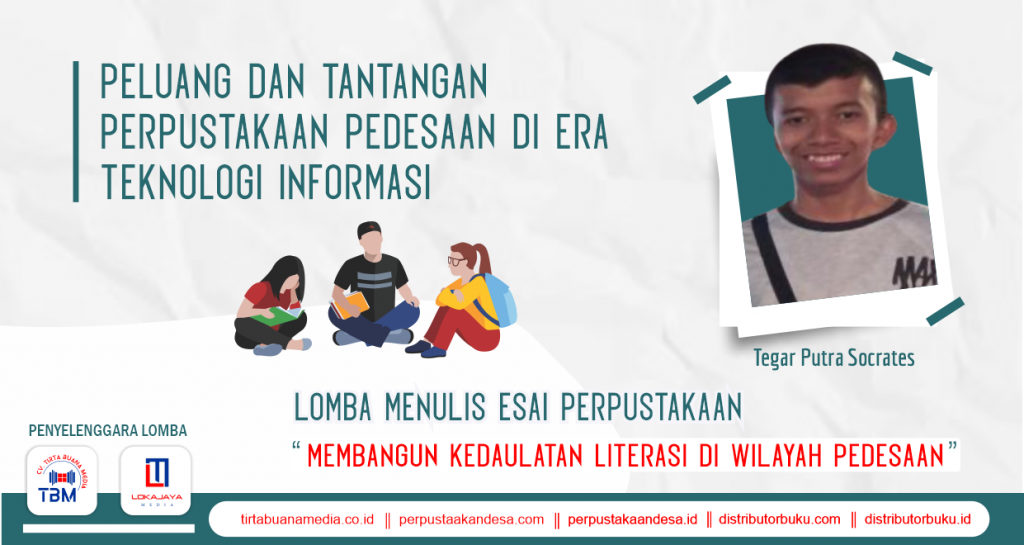
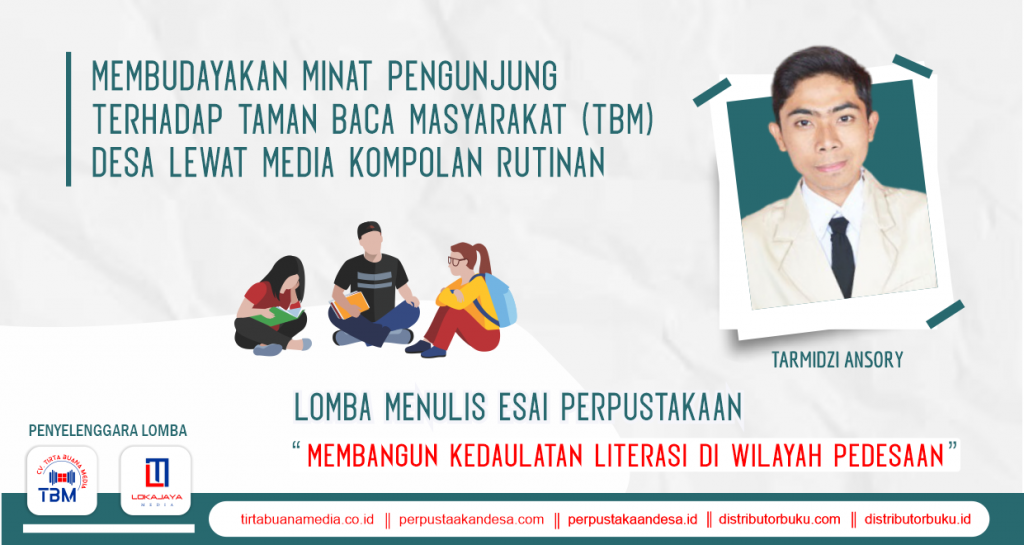
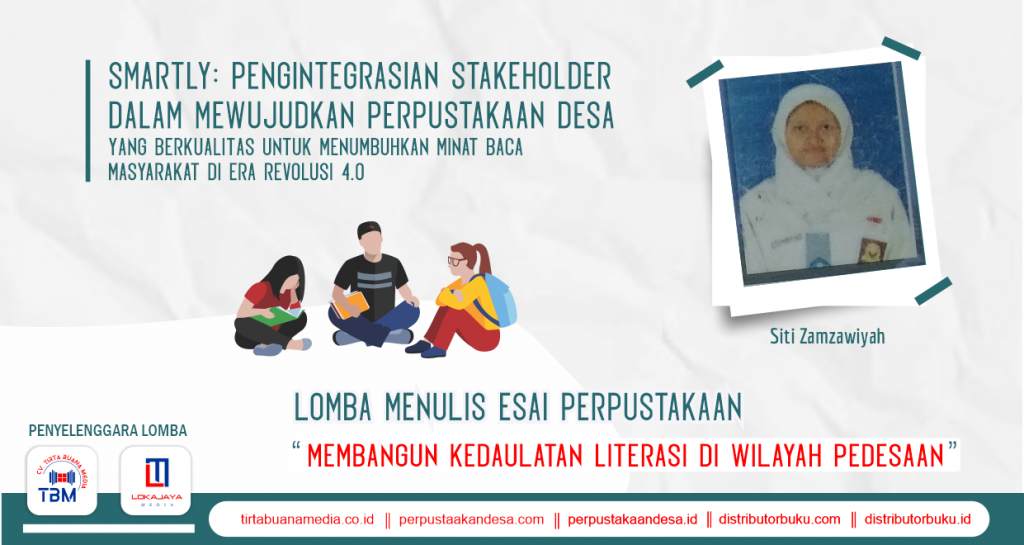
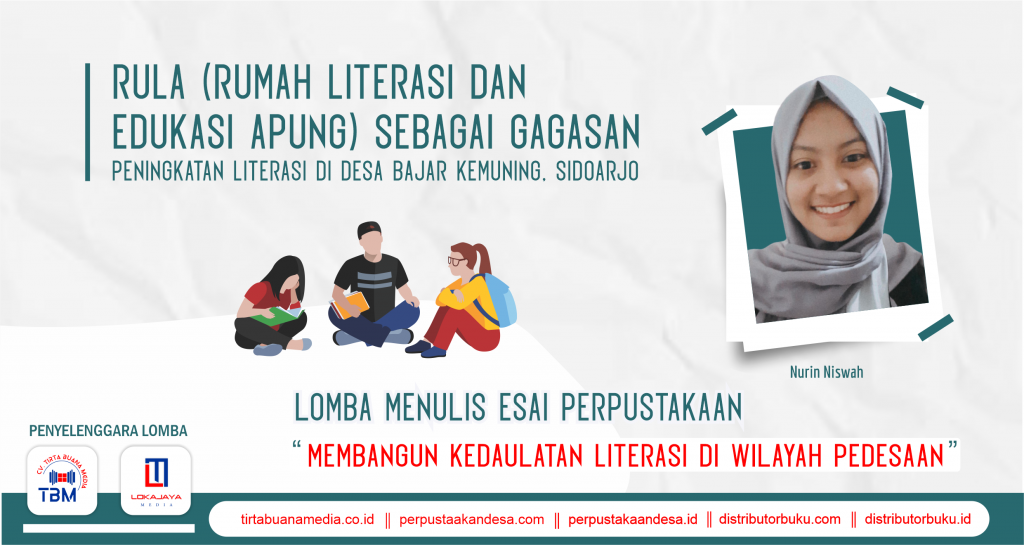
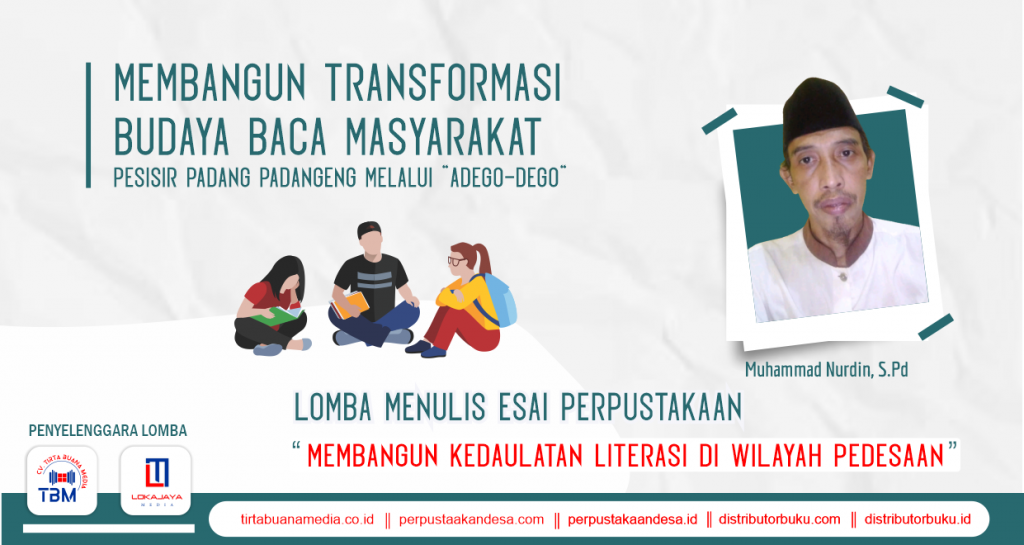

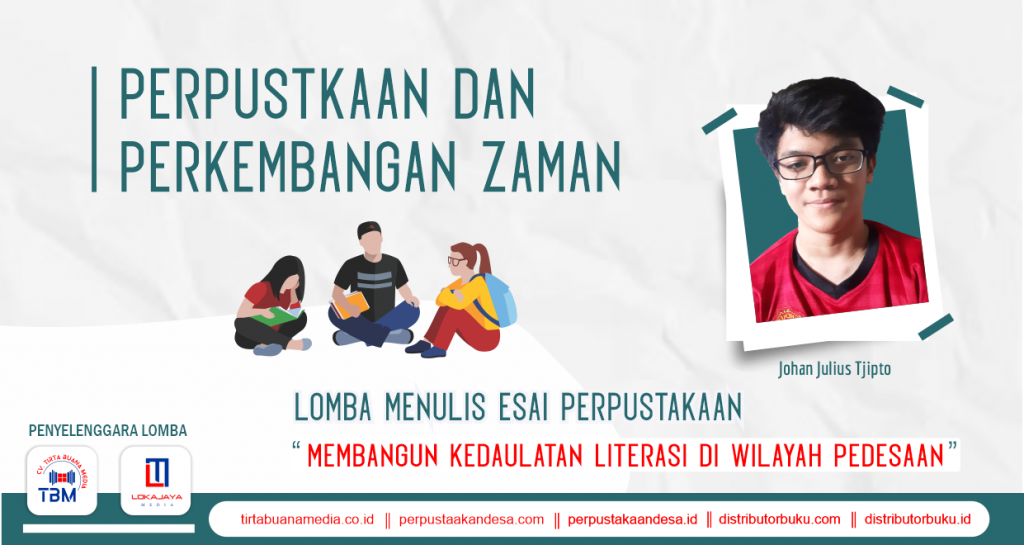
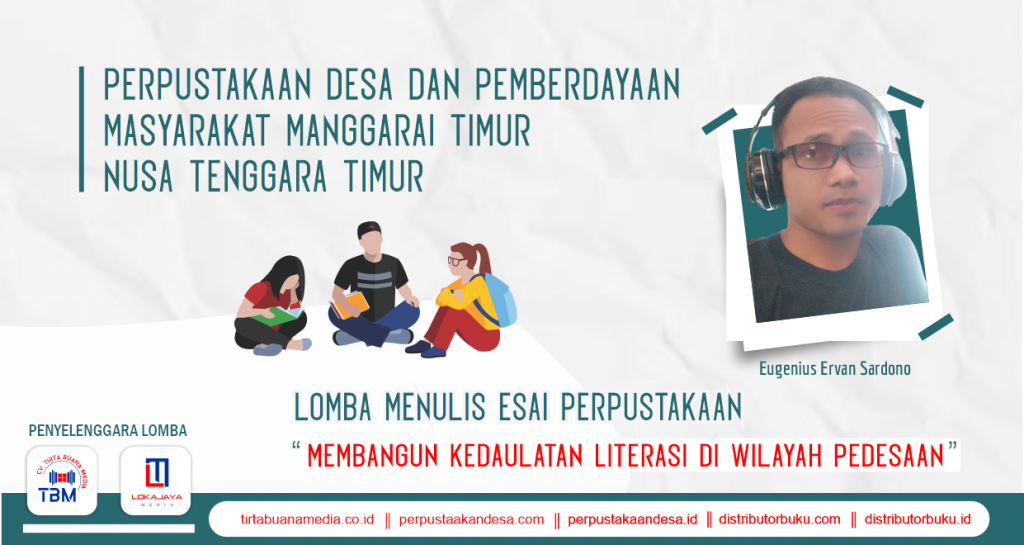
makasih ada yng share lg ifo bermanfaat
wih keren banget sharingnya
thx kabarnya yah gan. keren abis
thx kabarnya yah gan. keren abis
Keren bro… tetap semangat & sukses selalu