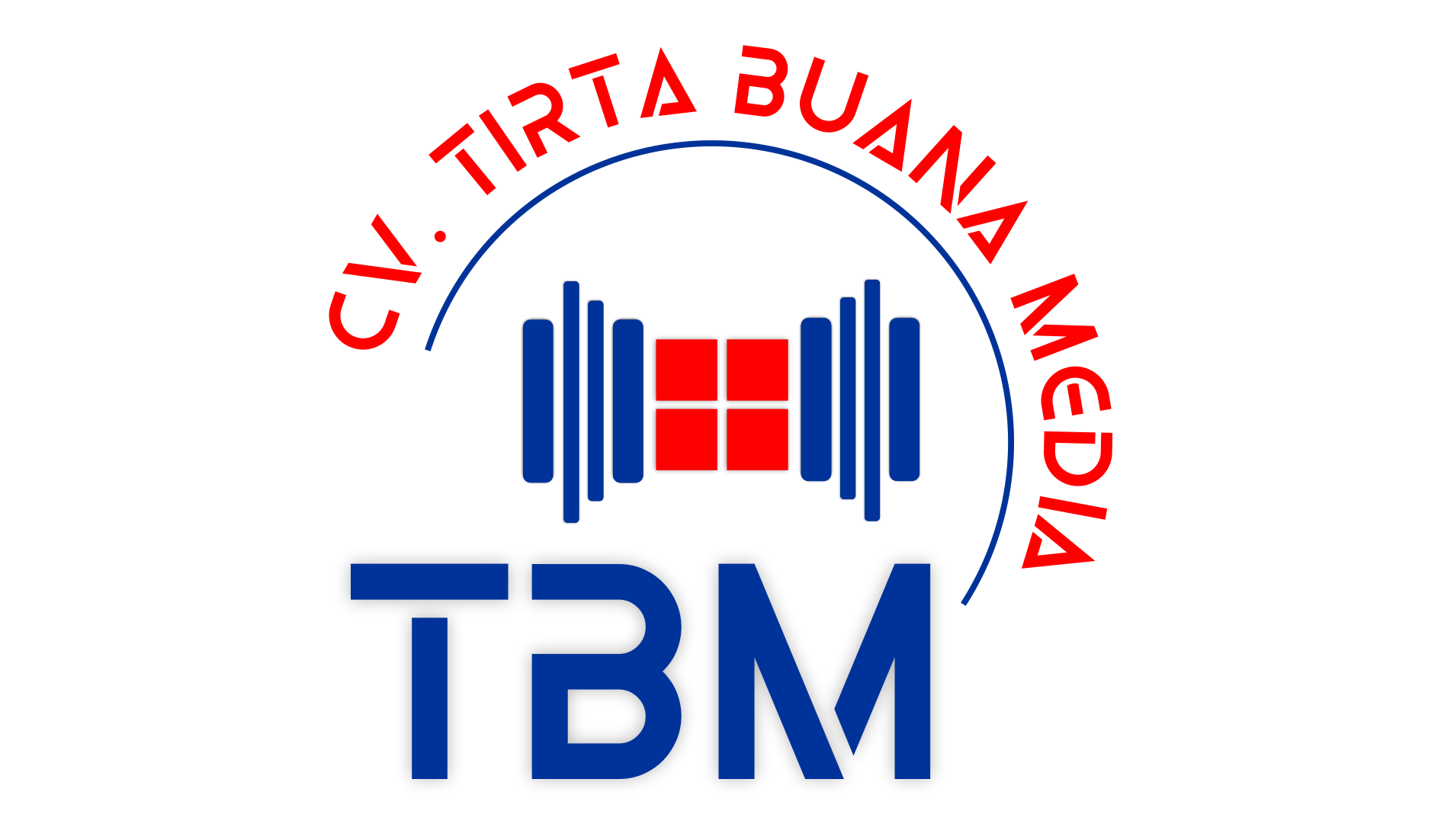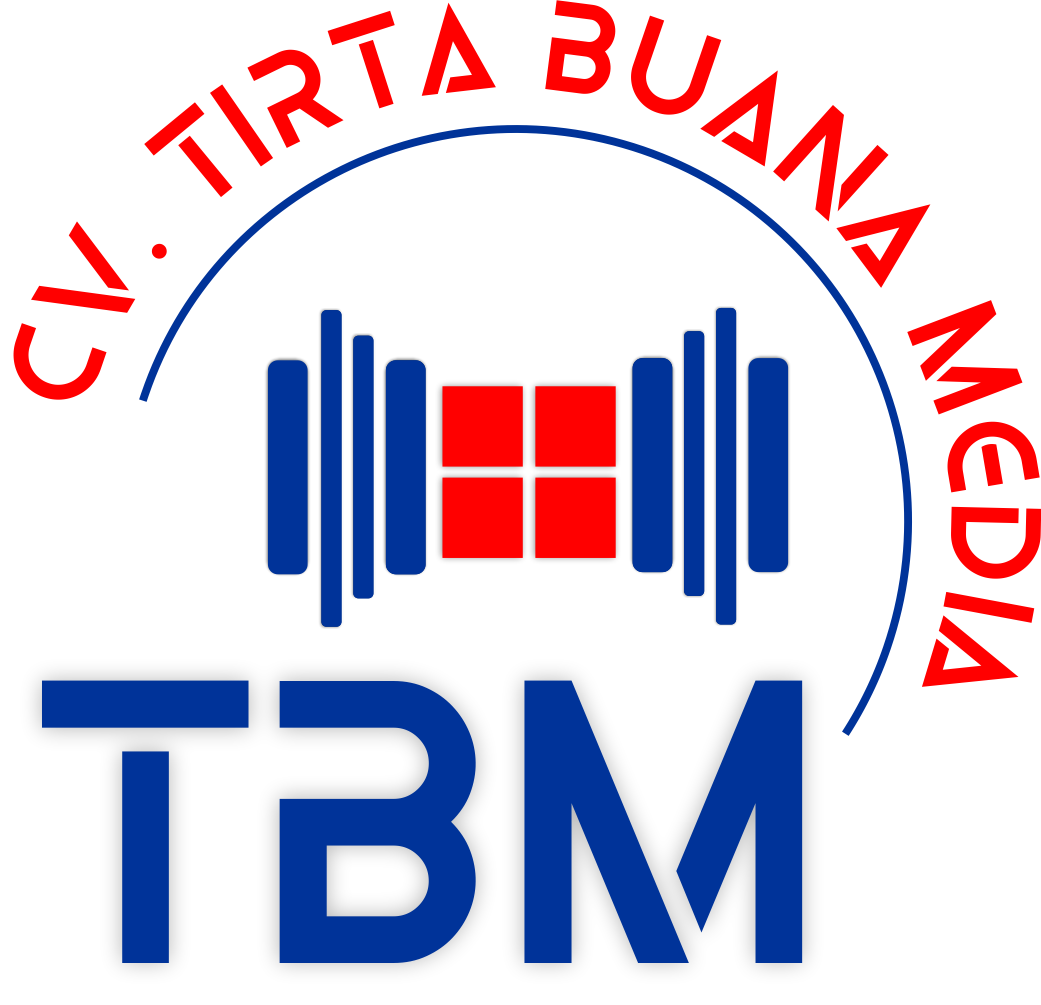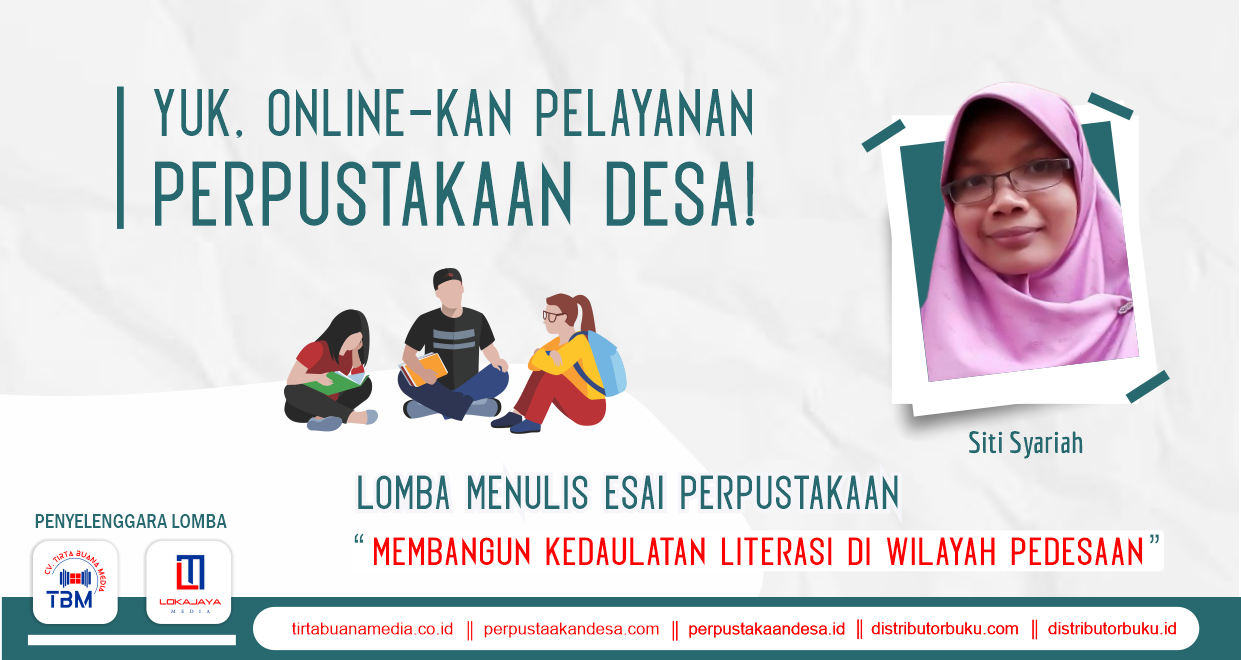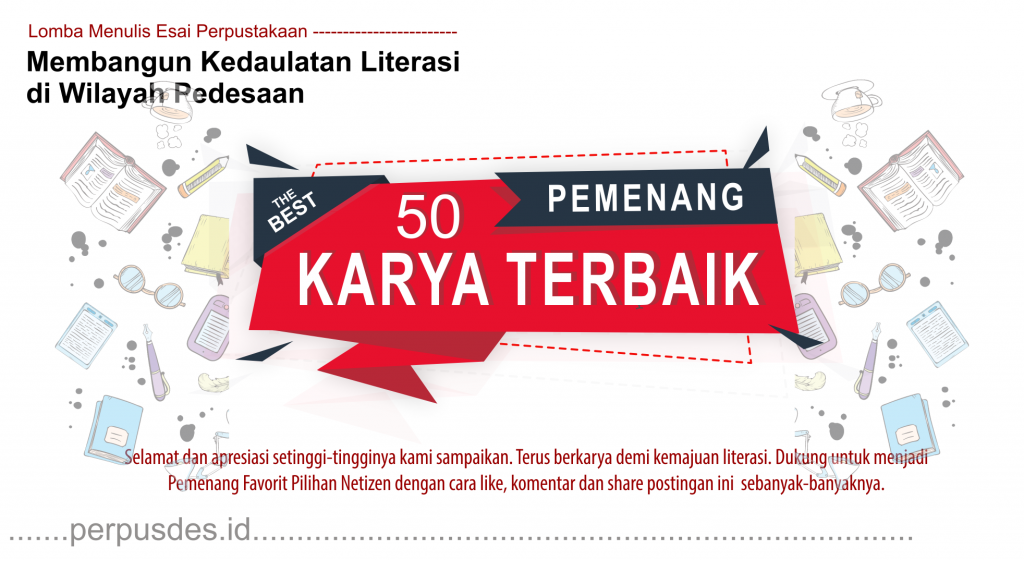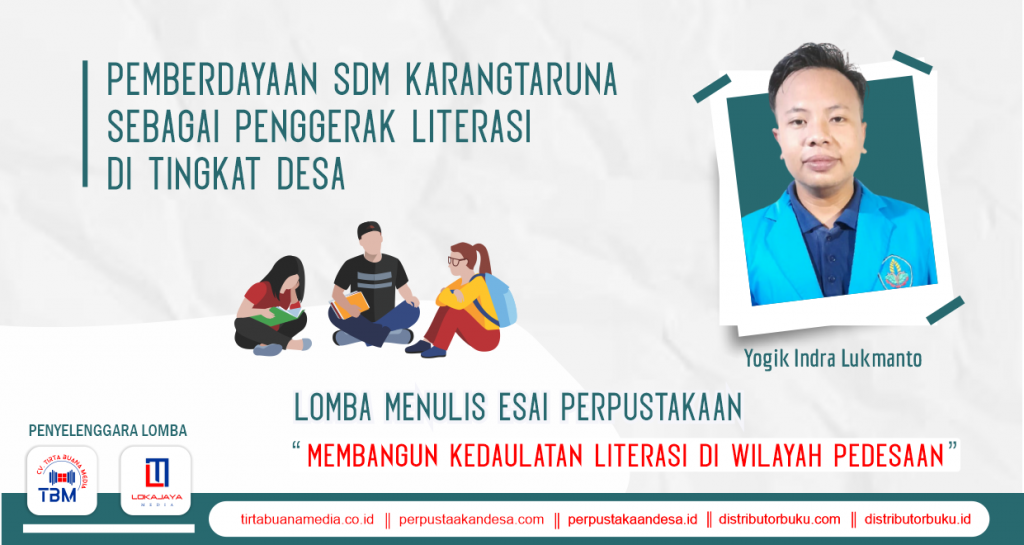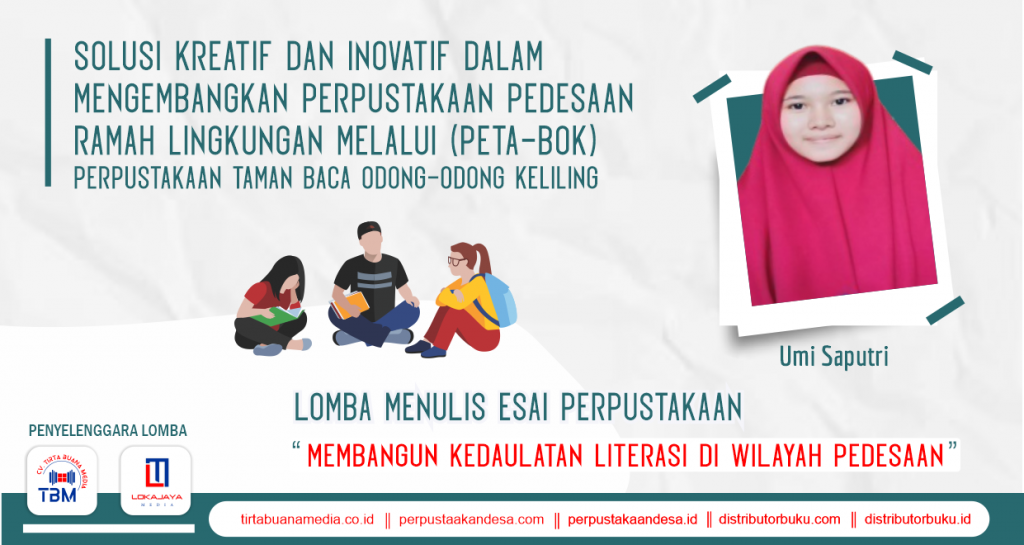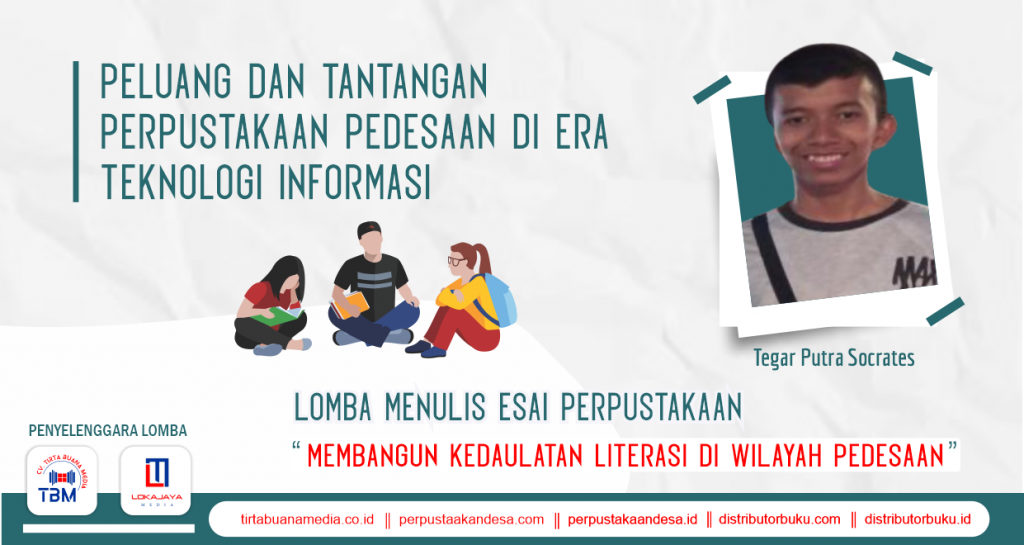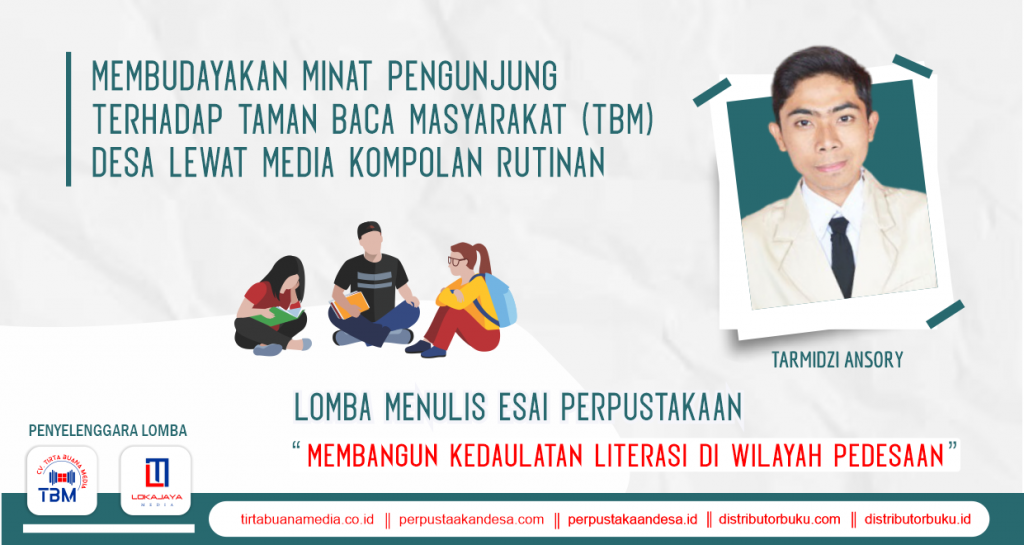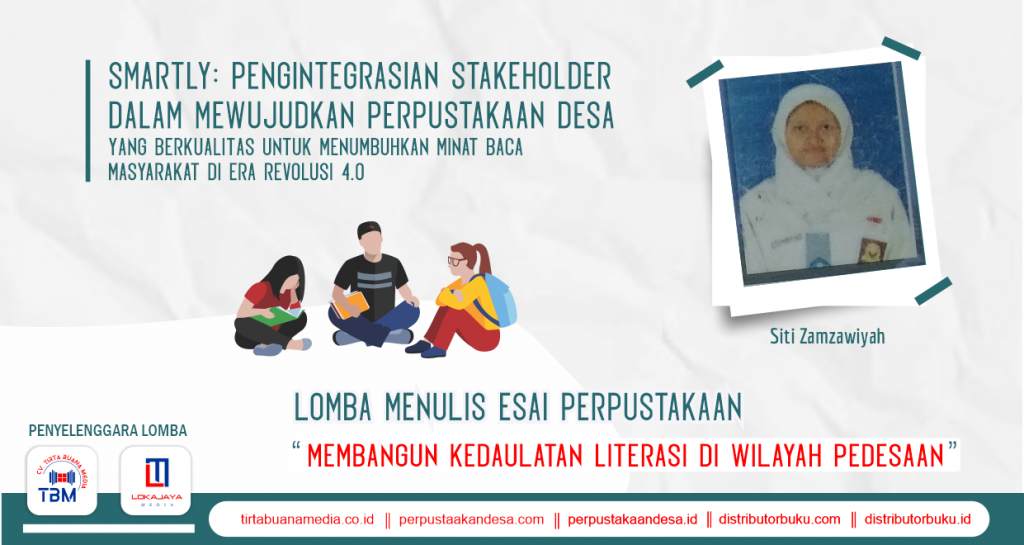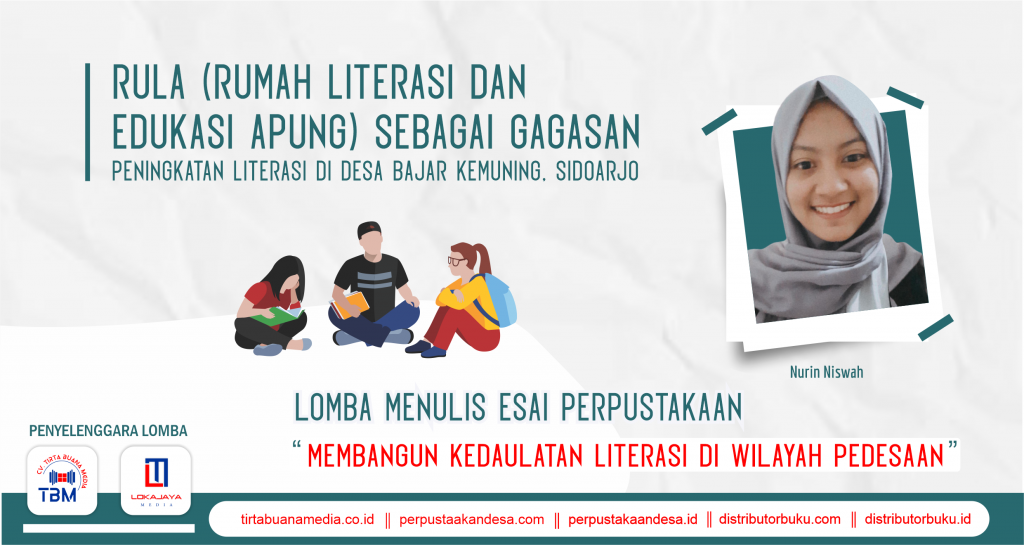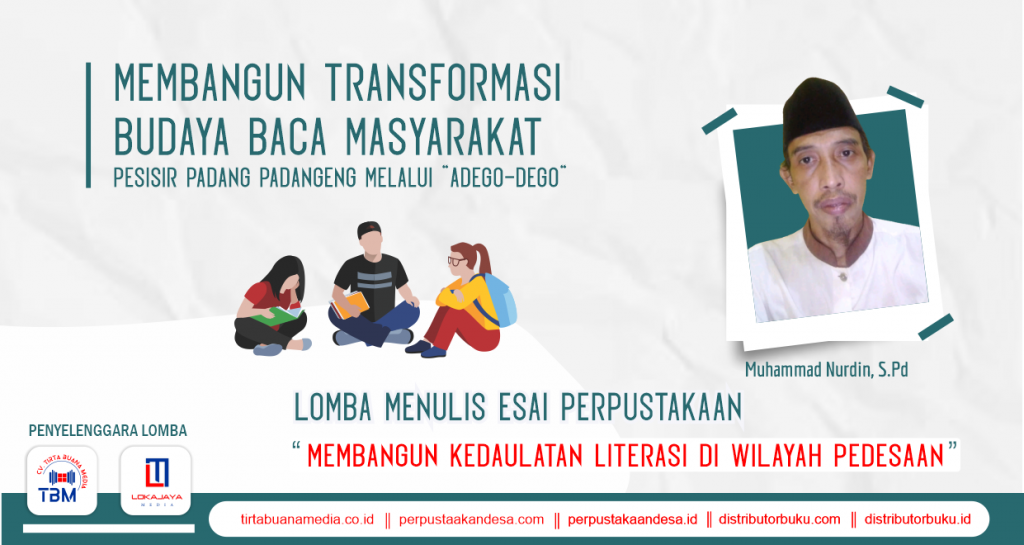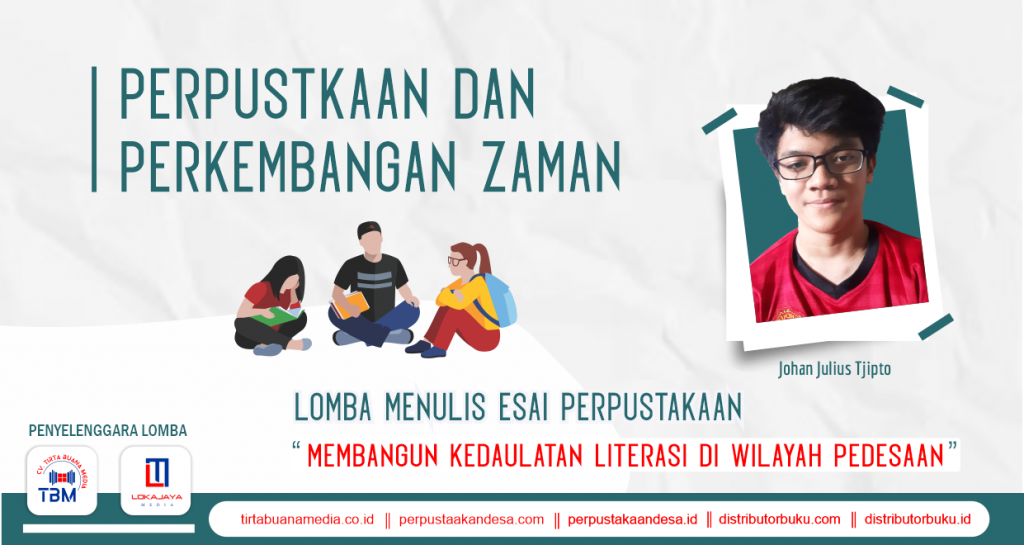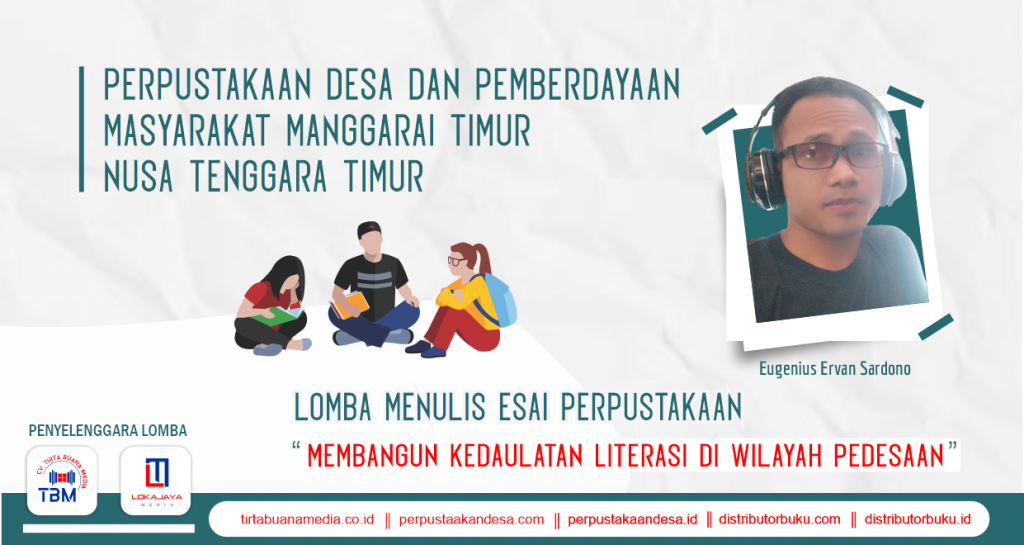Literasi merupakan kemampuan aksara yang erat kaitannya dengan kemampuan membaca dan menulis yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya peradaban. Karena ia merupakan pintu untuk mempelajari berbagai sumber ilmu pengetahuan yang lain, yang kemudian dapat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.
Mengingat urgesi literasi di tengah-tengah msyarakat Indonesia yang masih rendah, maka pemerintah mulai melegalisasi gerakan pendirian perpustakaan di setiap desa melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Landasan hukum tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang konsep perpustakaan desa, yaitu sebagai: “Wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.”
Dari konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa tujuan pendirian perpustakaan desa adalah untuk memudahkan masyarakat menjangkau sumber bacaan yang relevan dengan kebutuhan mereka, tanpa harus bersusah payah mencari sendiri ke pusat kota.
Namun dalam penyelenggaraannya, mengelola perpustakaan desa ternyata tidak semudah mendirikannya. Tantangan terbesar yang dihadapi terletak pada buruknya pengelolaan yang disebabkan kurangnya sumber daya masyarakat yang memiliki kecakapan khusus untuk mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan. Karena tak dapat dipungkiri, akibat kurangnya sosialiasi, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui keberadaan perpustakaan di desa mereka. Kalau pun mengetahui lokasinya, tidak sedikit masyarakat yang merasa enggan, bahkan segan untuk mendatangi perpustakaan tersebut karena kurangnya promosi.
Selain itu, pengelola perpustakaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan kampanye membaca pada seluruh lapisan masyarakat. Karena minat baca masyarakat yang tinggi adalah ruh dari perpustakaan. Jika tidak, dapat dipastikan perpustakaan desa hanya akan menjadi pajangan atau atribut pelengkap di sebuah desa. Karenanya, diperlukan upaya-upaya inovatif dan kreatif untuk memberdayaan perpustakaan desa sebagai ujung tombak terbentuknya budaya literasi di tengah masyarakat.
Seiring perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, orang-orang seringkali mengkambinghitamkan teknologi sebagai musuh terbesar literasi. Meski anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun sejatinya, teknologi dapat digunakan sebagai media kampanye yang efektif, salah satunya dengan menggunakan platform media sosial. Karena sebagian besar masyarakat paling cepat dan paling mudah ditemui melalui media sosial, maka ia pun dapat menjadi salah satu media yang paling efektif untuk mendukung pemberdayaan perpustakaan desa.
Langkah pertama, pengelola perpustakaan dapat membuat akun perpustakaan desa melalui berbagai platform media sosial yang dipakai sebagian besar masyarakat, seperti facebook fanpage atau instagram, tanpa luput memastikan setiap warga yang memilliki akun media sosial mem-follow akun media sosial perpustakaan desa mereka. Dengan demikian, sebagain besar masyarakat dapat mengetahui eksistensi perpustakaan di desa mereka.
Langkah kedua, dengan memanfaatkan fitur media sosial tersebut, pengelola perpustakaan dapat membuat katalog perpustakaan online dengan memajang setiap foto sampul koleksi buku yang dimiliki perpustakaan desa. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui jumlah dan jenis buku yang terpajang di perpustakaan desa, yang kemudian dapat dengan mudah mereka pilah-pilih sesuai kebutuhan dan keinginan.
Setelah menemukan target buku bacaan, setiap warga dapat meminjam buku tersebut secara online, yang kemudian akan diantarkan keliling ke rumah-rumah oleh petugas perpustakaan. Proses pengantaran buku keliling dapat dilakukan secara periodik setiap seminggu sekali. Proses pengembalian buku dapat dilakukan saat peminjaman di minggu berikutnya. Dengan cara ini, masyarakat dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan harus mendatangi perpustakaan desa secara langsung. Karena tak dapat dipungkiri, semakin hari masyarakat semakin menuntut kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan. Berbelanja kebutuhan pokok saja mereka lebih suka melakukannya secara Cash on Delivery, apalah lagi untuk urusan membaca.
Langkah ketiga, pengelola perpustakaan berupaya mendorong masyarakat yang aktif meminjam dan membaca buku dari perpustakaan desa untuk menulis resensi buku yang mereka baca di halaman akun media sosial mereka. Berkaitan dengan ini, pengelola dapat menyelanggarakan lomba menulis resensi buku untuk lebih memotivasi masyarakat pembaca. Menulis resensi buku di media sosial merupakan salah satu cara untuk mengkampanyekan gerakan membaca di tengah masyarakat. Karena seperti halnya produk bisnis, buku juga butuh promosi agar orang-orang tertarik untuk membacanya. Orang-orang secara alamiah tertarik untuk membaca buku yang dianggap orang lain menarik untuk dibaca. Di sinilah letak kekuatan promosi dari mulut ke mulut.
Langkah keempat, pengelola perpustakaan berupaya menjadi jembatan antara toko buku dengan pembaca. Ketika masyarakat telah mulai keranjingan membaca, tak menutup kemungkinan mereka memiliki keinginan untuk memiliki beberapa koleksi buku favorit di rumahnya. Dalam hal ini, pengelola perpustakaan desa dapat menjadi distributor buku bagi masyarakat pembaca di desanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan buku secara online maupun melalui katalog-katalog buku yang disebarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau buku yang ingin mereka beli secara langsung.
Gerakan inovatif tersebut di atas tentu tak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sumber dana dan sumber daya manusia yang memdai. Bagaimanapun juga, untuk menghidupkan perpustakaan desa, uang dan orang adalah elemen terpenting.
Pendanaan untuk biaya operasional dan juga upah pengelola perpustakaaan sejatinya tak perlu dibingungkan, karena sumber pendanaanya telah jelas disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, yaitu dapat bersumber dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Sumber Dana Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Kemudian, untuk mendapatkan tenaga pengelola yang kompeten, pemerintah desa dapat melakukan seleksi pengelola perpustakaan dengan memperhatikan beberapa kualifikasi penting, seperti latar belakang pendidikan, kompetensi sikap dan spiritual dan yang tak kalah penting adalah passion dalam dunia literasi. Karena orang yang memiliki hasrat yang besar dalam dunia literasi lah yang dapat bekerja dengan sepenuh hati mengelola perpustakaan desa.
Akhirnya, langkah-langkah di atas dapat berjalan sesuai harapan apabila terjalin komitmen yang kuat antara pengelola perpustakaan dengan kepala desa sebagai pembina perpustakaan dan juga dengan berbagai tokoh yang menjadi panutan di tengah masyarakat. Karena menanamkan budaya literasi melalui pemberdayaan perpustakaan desa bukanlah pekerjaan singkat. Ia harus terus-menerus dipupuk dan ditumbuhsuburkan agar dapat memberi dampak bagi pendidikan dan pembangunan nasional.
Referensi:
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2001. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS
 Siti Syariah lahir di Lombok Barat pada tanggal 14 Pebruari 1990. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Mataram pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sejak tahun 2013, ia adalah guru honorer di beberapa sekolah di Lombok Utara. Pada tahun 2020 memutuskan berhenti sejenak dari dunia mengajar untuk melanjutkan pendidikan magister pada jurusan Applied linguistics. Ia tinggal di kaki Gunung Rinjani di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB bersama suami dan kedua anaknya. Ia dapat dihubungi melalui nomor Whats Up: 0823 4071 0938.
Siti Syariah lahir di Lombok Barat pada tanggal 14 Pebruari 1990. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Mataram pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sejak tahun 2013, ia adalah guru honorer di beberapa sekolah di Lombok Utara. Pada tahun 2020 memutuskan berhenti sejenak dari dunia mengajar untuk melanjutkan pendidikan magister pada jurusan Applied linguistics. Ia tinggal di kaki Gunung Rinjani di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB bersama suami dan kedua anaknya. Ia dapat dihubungi melalui nomor Whats Up: 0823 4071 0938.