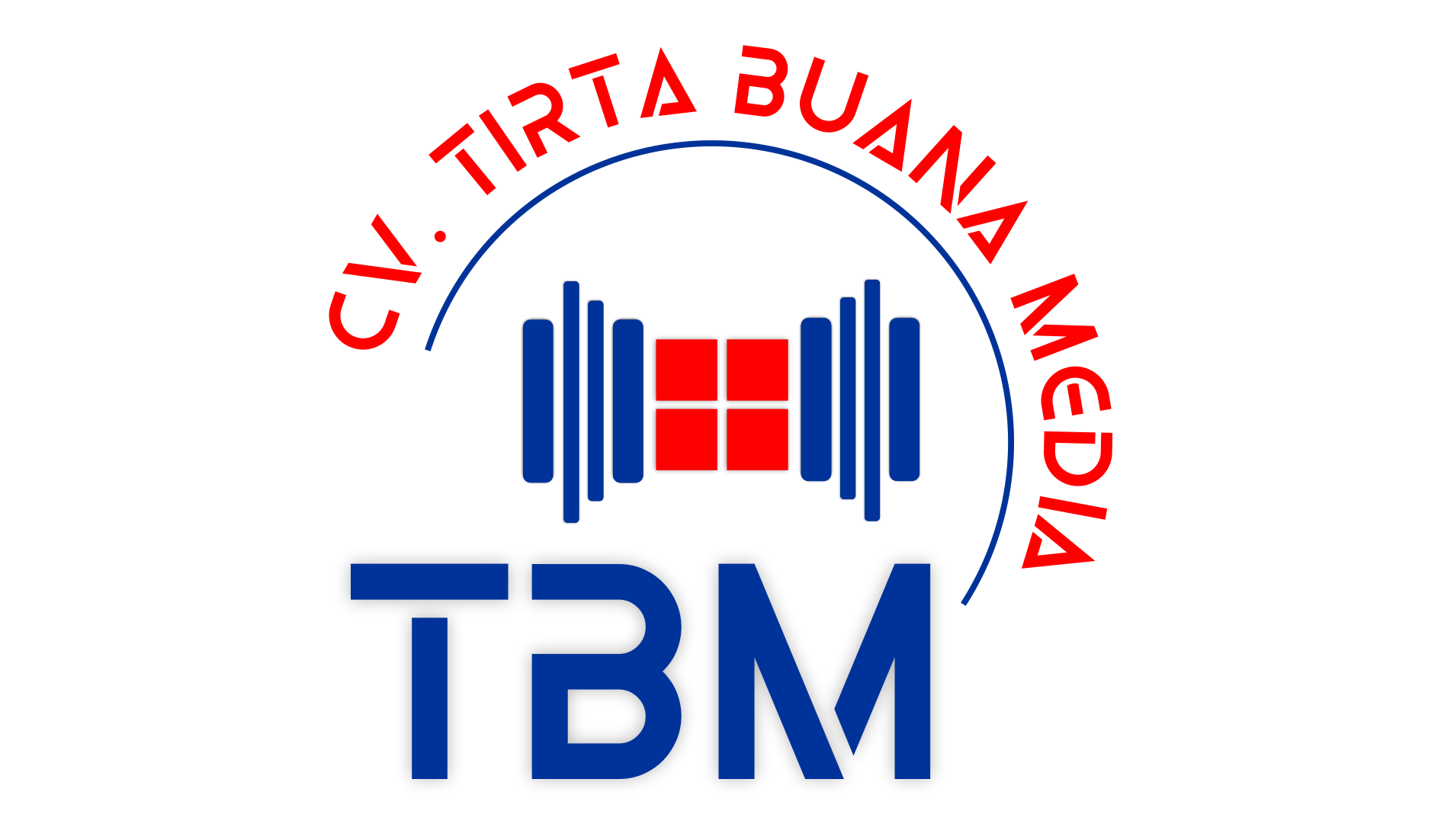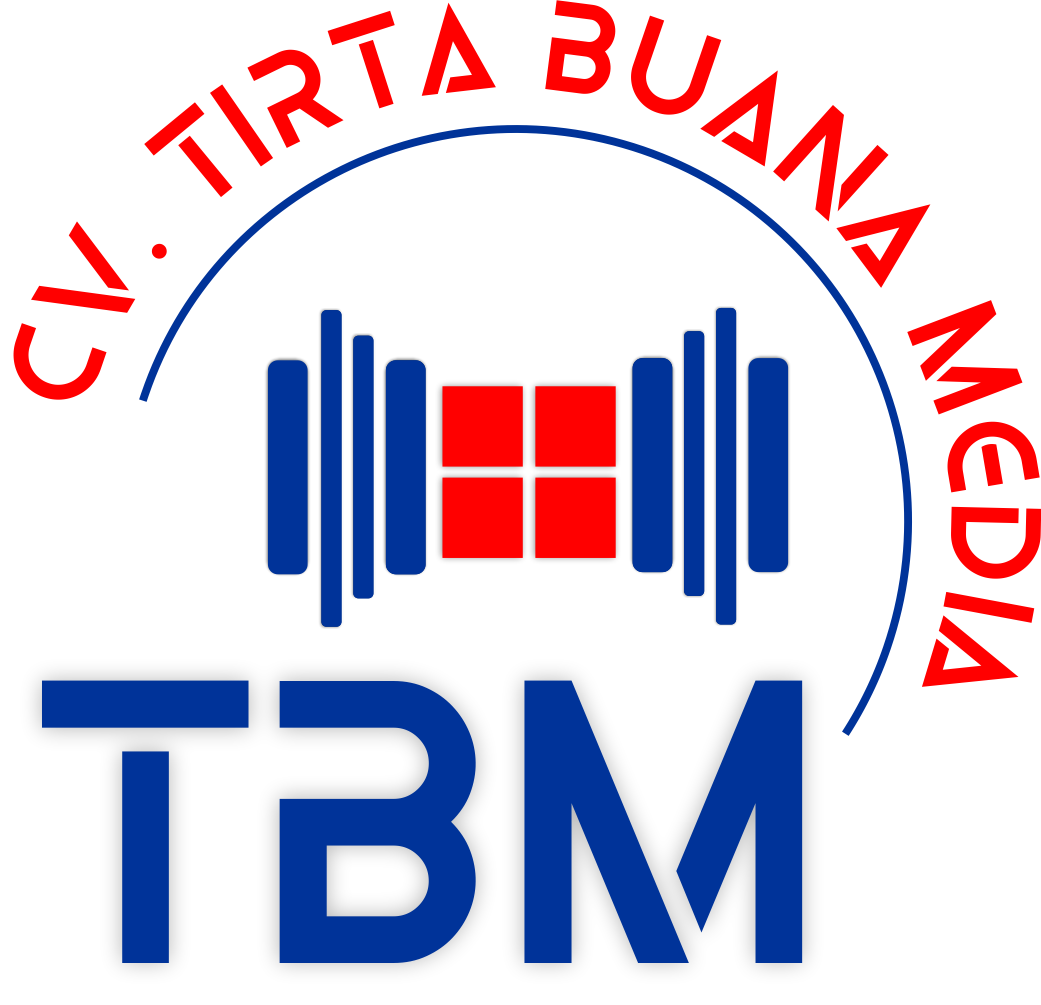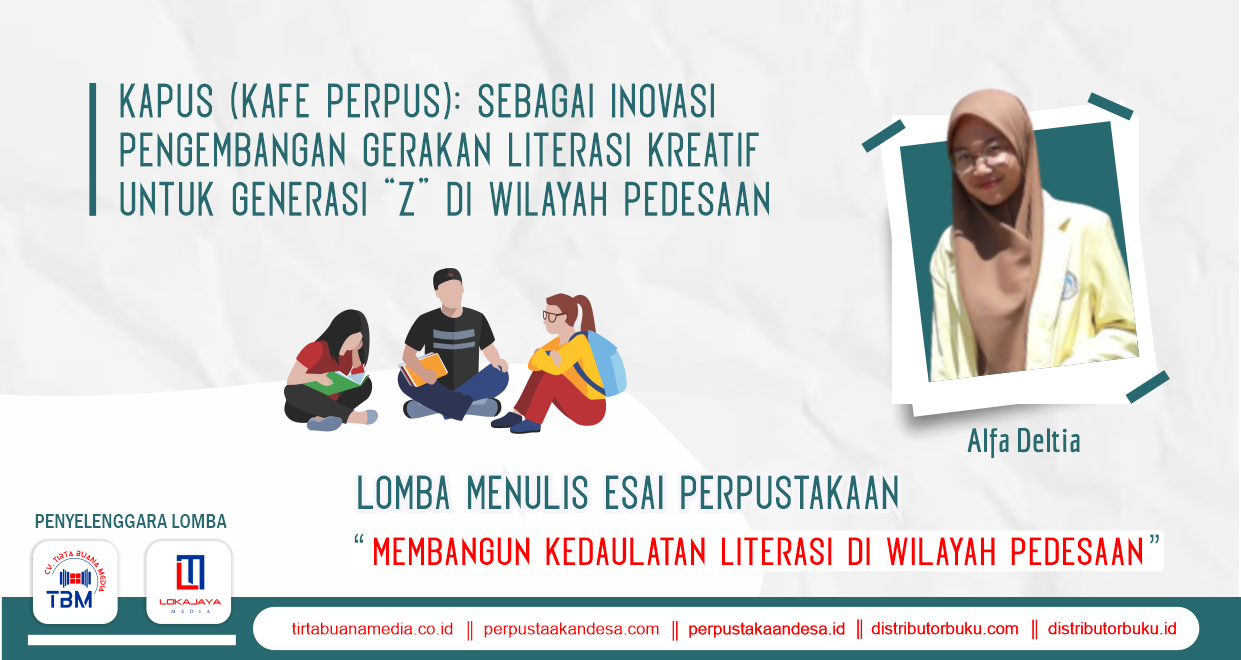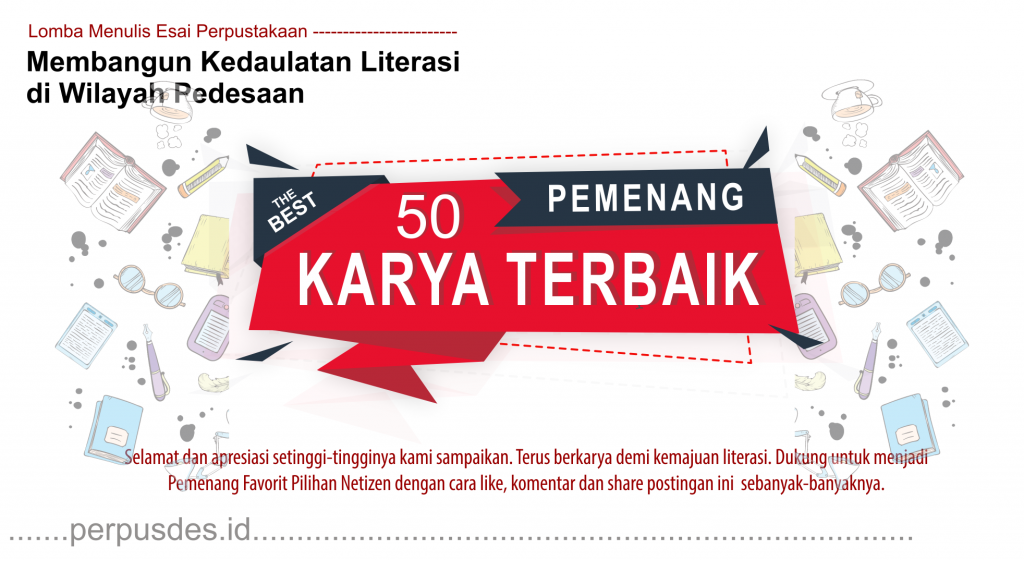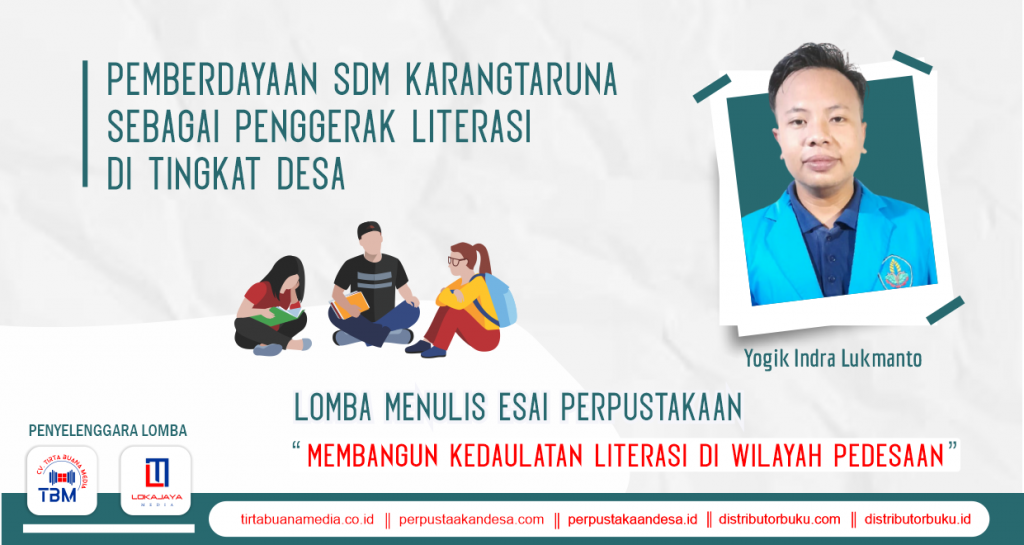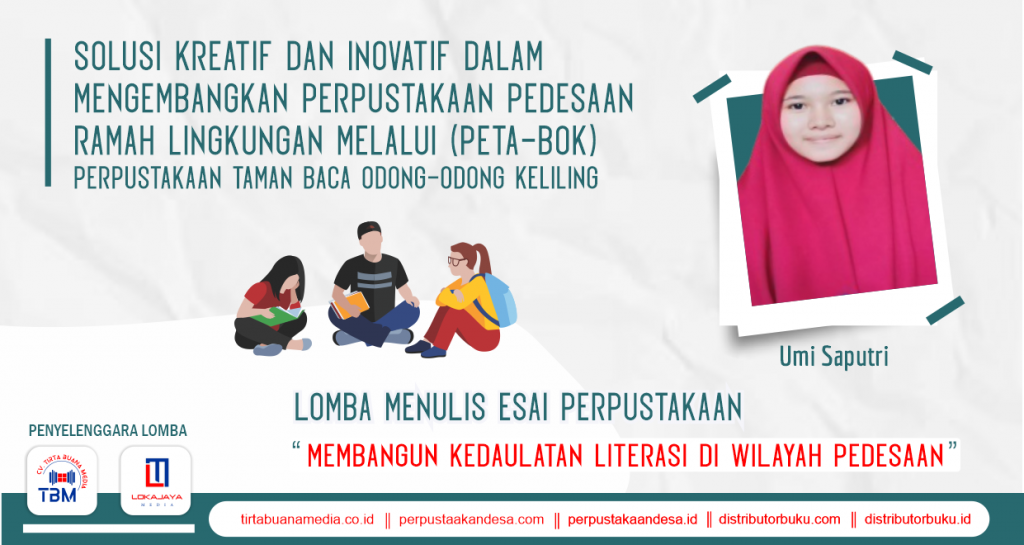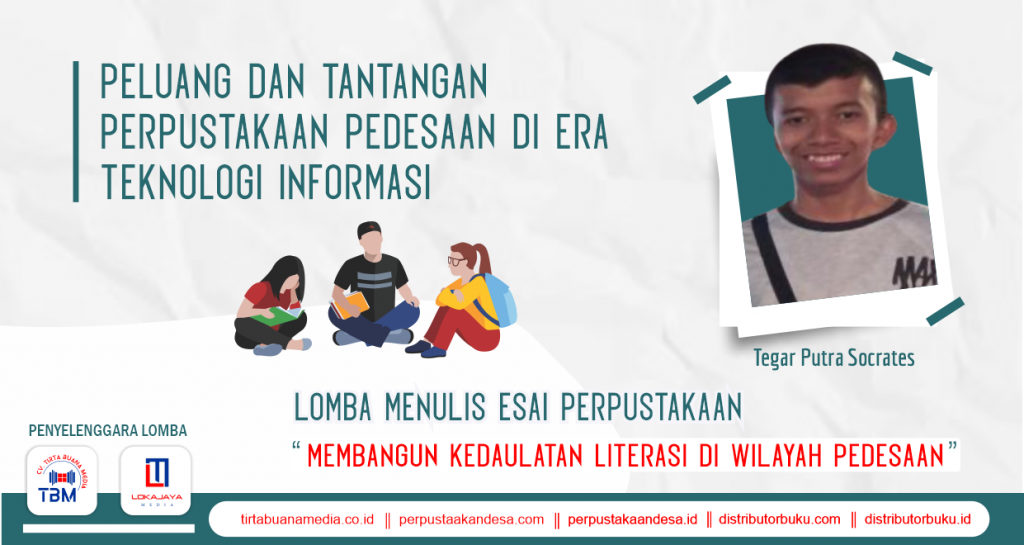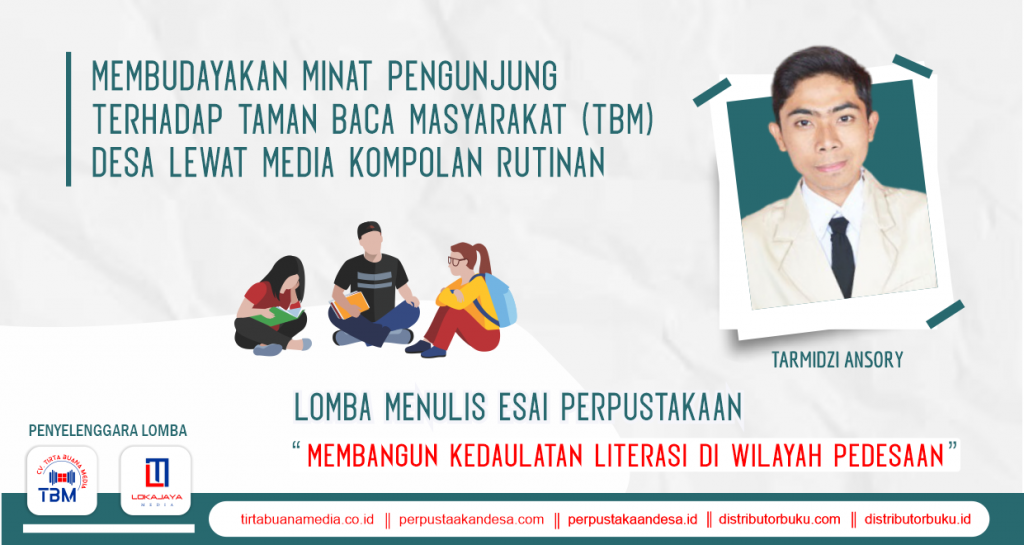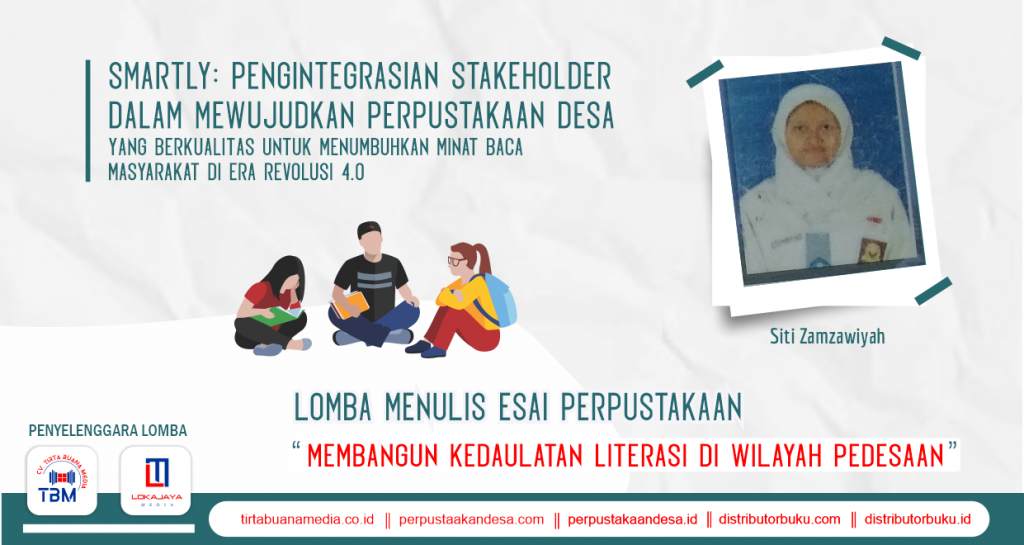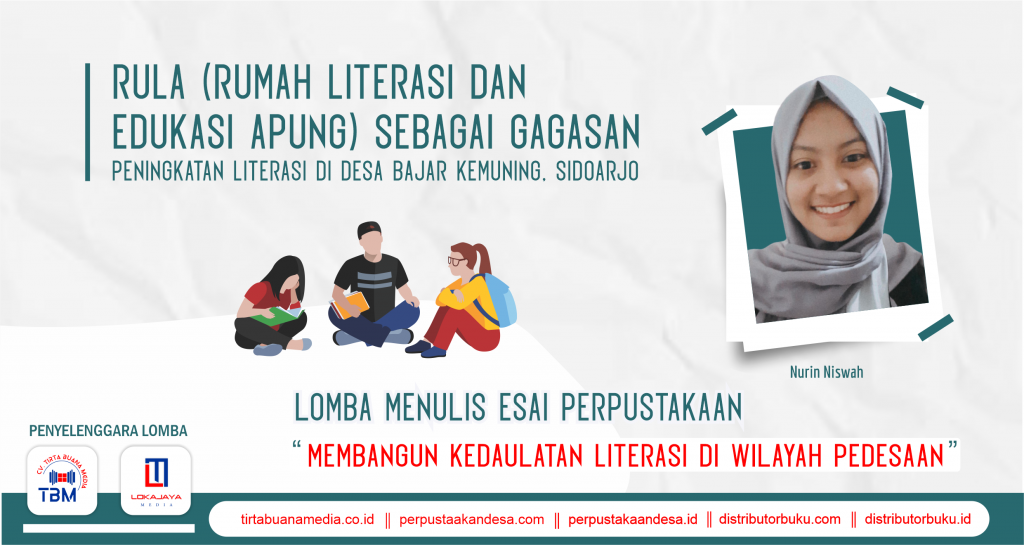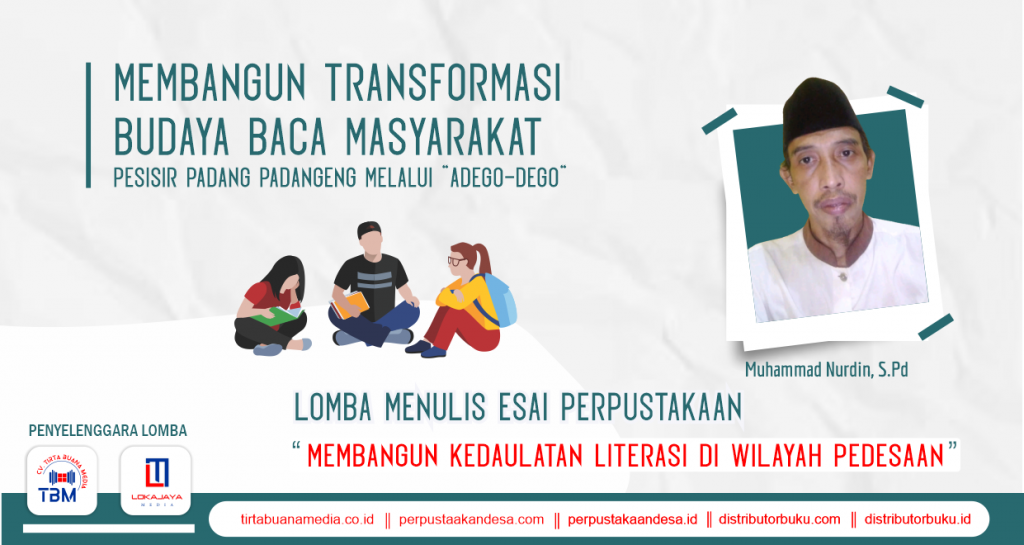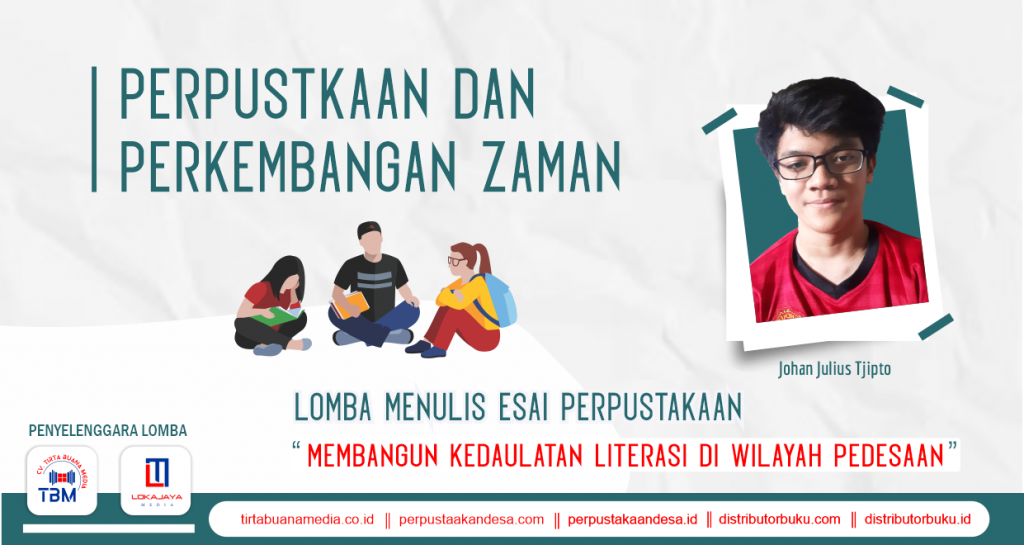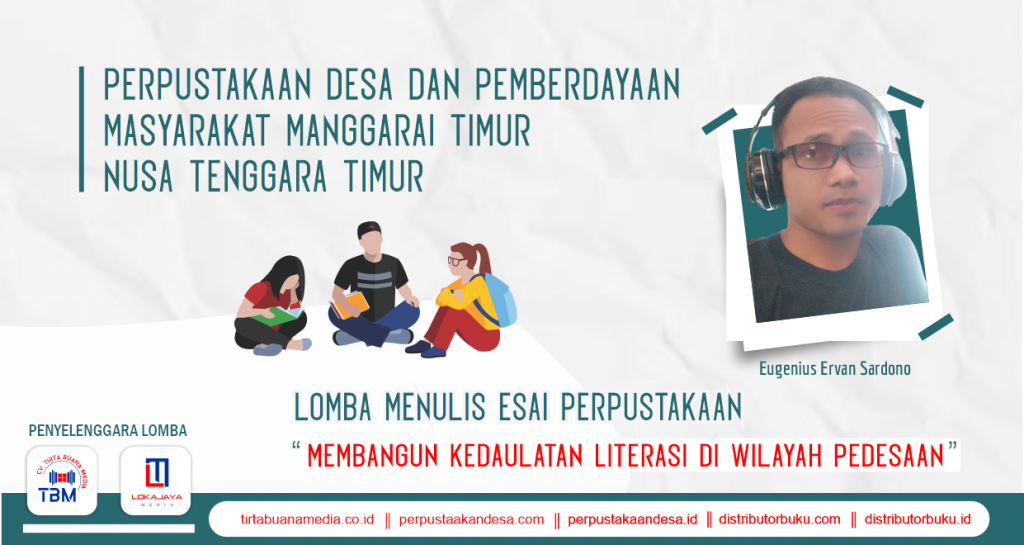Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan berliterasi yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian PISA (Progremme for International Student Assessment) tahun 2006 siswa Indonesia berada pada posisi 48 dari 56 negara di dunia dan pada tahun 2012 hasil peneltian PISA menempatkan siswa Indonesia berada pada posisi kedua terburuk atau posisi 64 dari 65 negara. Kemudian hasil PISA tahun 2019 menunjukkan skor membaca siswa Indonesia kembali menurun 26 poin. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena pendidikan Indonesia sampai saat ini tidak memberikan porsi yang besar terhadap upaya untuk membangun literasi membaca siswa (Kristanti, 2019:3). Selain itu, berdasarkan statistik UNESCO indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya dalam setiap 1000 orang, hanya ada satu orang yang mempunyai minat membaca. Indikator rendahnya minat baca bisa dilihat dari jumlah buku yang terbit di Indonesia. Buku yang terbit tiap tahun baru mencapai angka 5000-10.000 judul buku pertahun. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai angka 15.000 judul buku pertahun, dan angka lebih dari 100.000 judul buku di Inggris per tahun (Hudayani dalam Nafisah, 2014:71).
Gaya pemahaman setiap generasi memiliki perbedaaan. Menurut Yanuar (dalam Saputra, 2020:158-159) manusia yang lahir pada tahun 1980-1995 yang disebut generasi Y banyak belajar melalui email, sms dan media sosial. Sedangkan generasi Z merupakan manusia yang lahir pada tahun 1995-2010 lebih banyak menghabiskan waktu melalui gaming, headset, browsing melalui PC (Personal Computer). Pengaruh gadget saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Dimulai dengan rendahnya minat baca terhadap buku, beralih menggunakan gadget yang canggih membuat budaya menulis dan membaca mulai ditinggalkan. Generasi Z sangat merasakan dampak adanya kecanggihan ini, karena mereka terlahir ketika Internet sudah banyak bermunculan sehingga mengakibatkan tergusurnya kearifan lokal disekeliling mereka.
Kemampuan generasi Z dalam mengoperasikan komputer seolah menjadi sahabat mereka. Selain itu generasi Z dikenal sangat native and technologically terhadap bermacam-macam perangkat elektronik yang modern, mudah beradaptasi, dan mampu mengeksplorasi hal-hal yang ada didalamnya. Generasi Z lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah dengan bermain gadget, mereka menganggap lingkungan yang ada disekitar mereka bukanlah hal yang menarik bagi mereka, karena bagi mereka pertemuan tidak harus berada dalam suatu ruang berbentuk fisik, melainkan melalui dunia maya yang menjadi ruang mereka sesungguhnya (John dan Bobby dalam Saputra, 2020:163).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pada saat ini gerakan literasi tidak hanya diakomodir oleh Pemerintah Pusat, masyarakat luas juga sudah membuat gerakan literasi yang diakomodir melalui Pemerintah daerah setempat untuk membuka ruang pada terbukanya gerakan literasi. Gerakan literasi tidak hanya dilakukan di sekolah atau lingkungan akademis saja, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Saputra, 2020:156-157). Namun dalam prakteknya, wadah yang menampung aktivitas minat baca seperti perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, tempat-tempat bacaan, sanggar-sanggar baca yang disediakan oleh pemerintah atau swasta jumlahnya terbatas. Perpustakaan umum sebagai salah satu tempat mendapatkan bahan bacaan bagi masyarakat hanya berkisar 2.585 perpustakaan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang menembus angka 200 juta jiwa, sehingga jika dirasionalkan maka satu perpustakaan umum terpaksa melayani hampir 85 ribu penduduk. Dari jumlah perpustakaan yang ada pun masih banyak yang sifatnya hanya sebagai “gudang buku” saja (Nafisah, 2014:73).
Perpustakaan mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan nonformal, agen perubahan, dan agen pembangunan bagi masyarakat sekelilingnya. Setiap perpustakaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama termasuk perpustakaan di wilayah pedesaan yaitu menghimpun, memelihara, dan memberdayakan koleksi yang dimilikinya. Fungsi spesifik perpustakaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 3. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Bahaudin dan Joko, 2019:61). Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan desa yang tidak memiliki perpustakaan, jikalau ada perpustakaan tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran aktif dari masyarakat dan atau pemerintah desa dalam mengembangkan perpustakaan desa, seperti kurangnya pengadaan koleksi perpustakaan, kurangnya peningkatan sarana dan fasilitas, kurangnya pelestarian perpustakaan, dan kurangnya pengembangan sumber daya perpustakaan lainnya. Padahal masyarakat dan pemerintah desa merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan, kemajuan, dan peningkatan perpustakaan desa.
Keberadaan perpustakaan perlu dipersepsi sebagai lembaga pendidikan alternative yang memiliki keberhasilan tersendiri yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara fungsional dan proposional. Dengan demikian saya memberikan solusi yang dapat dijadikan sebagai langkah untuk mengembangkan gerakan literasi khususnya bagi generasi Z di wilayah pedesaan yaitu dengan membuat KAPUS (Kafe Perpus). KAPUS merupakan perpus berbentuk kafe yang menyediakan buku-buku yang dapat menunjang pengetahuan para pengunjungnya. KAPUS bertujuan untuk menarik perhatian generasi Z yang banyak menghabiskan waktunya di rumah dengan gadget dan menganggap lingkungan disekitar tidak menarik, karena pada saat sekarang ini sebagian dari generasi Z menyukai tempat di luar rumah yang nyaman dan asik untuk nongkrong, mengerjakan tugas kuliah, berdiskusi, ataupun kegiatan yang lainnya. Di dalam KAPUS selain disediakan buku-buku juga akan disediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan yang wajib dibeli oleh pengunjung. Hal ini dilakukan agar para pengunjung dapat membaca buku atau berdiskusi dengan santai, serta uang hasil minuman atau makanan yang terjual dapat digunakan untuk menambah buku atau untuk didonasikan ke masyarakat desa yang membutuhkan.
KAPUS bisa digunakan melalui dua tahap, yaitu KAPUSLING dan KAPUSRUM . KAPUSLING (Kafe Perpus Keliling) dioperasikan dengan cara berkeliling desa menggunakan mobil dan berhenti di tempat-tempat yang memunginkan para pengunjung mendatanginya. Seperti di lapangan, di sekolah, di kampus, di taman, dan lain sebagainya. Mobil KAPUSLING yang digunakan bisa disediakan satu perkecamatan atau perkabupaten yang pengoperasiannya akan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan pemerintah desa setempat. Di dalam mobil tersebut disediakan buku-buku yang dapat dipilih pengunjung sesuai keinginan atau kebutuhannya, disediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan serta disediakan juga meja dan kursi. Buku-buku yang disediakan akan diganti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa setempat.
Sementara KAPUSRUM (Kafe Perpus Rumah) merupakan perpus berbentuk kafe sebagai bentuk pengembangan dari KAPUSLING. Jadi, KAPUSRUM hanya bisa dioperasikan jika pengunjung dari KAPUSLING sudah banyak sehingga sudah tidak efektif lagi jika hanya dioperasikan dengan berkeliling menggunakan mobil. KAPUSRUM berbentuk seperti kafe-kafe pada umumnya, bedanya di KAPUSRUM disediakan buku-buku yang jumlahnya lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan KAPUSLING, serta disediakan juga musik akustik pada ha ri-hari tertentu agar KAPUSRUM terlihat lebih kekinian yang disesuaikan dengan selera generasi Z. Walaupun KAPUSRUM didirikan di wilayah pedesaan tidak menutup kemungkinan jika KAPUSRUM dapat menjadi salah satu pembangunan pedesaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut.
Pihak-pihak yang berperan dalam KAPUS selain pemerintah daerah atau desa yaitu pustakawan sebagai tenaga khusus yang ahli dalam ilmu kepustakaan, jika tidak ada bisa digantikan dengan guru atau dosen yang paham dengan ilmu kepustakaan. Hal ini dibutuhkan agar perpus tidak menjadi seperti gudang buku saja melainkan perpus yang dapat menjadi sarana penunjang pengembangan pengetahuan masyarakat. Selain itu dibutuhkan relawan yang mau berpartisipasi aktif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat seperti dari mahasiswa dan siswa SMA/sederajat. Relawan ini akan bertugas sebagai orang yang menjalankan KAPUSLING dan KAPUSRUM. Jika jumlah relawan banyak dan maka akan dibagi tugas perindividu mengenai apa saja yang harus dilakukannya, namun jika jumlah relawan sedikit maka pemerintah desa bisa membuka lowongan pekerjaan yang difokuskan untuk masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan. Selain bertugas dalam menjalankan KAPUSLING dan KAPUSRUM relawan juga bertugas mengadakan penyuluhan mengenai manfaat membaca dan memperkenalkan KAPUS kepada masyarakat di desa tersebut.
Melalui KAPUS sebagai gerakan literasi inovatif dan kreatif akan dapat mengembangkan minat baca generasi Z di wilayah pedesaan. Walaupun KAPUS difokuskan untuk generasi Z tetapi KAPUS juga bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. KAPUS yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kafe-kafe atau perpus-perpus yang lain dapat membuat generasi Z teralihkan perhatiannya dari gadget ke lingkungan sekitar yang juga dapat menambah pengetahuan dan melatih kepedulian sosialnya karena KAPUS tidak hanya kafe yang menyediakan buku atau makanan dan minuman saja tetapi sebagai salah satu langkah dalam pengembangan pembangunan dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan.
Referensi:
- Bahaudin, M. Syafik, dan Joko Wasisto. 2019. Peran Perpustakaan Desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang). Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol.7, No.2.
- Kristanti, Anjar Aprilia. 2019. Program Madrasah Membaca sebagai Salah Satu Penanggulangan Tragedi Literasi pada Generasi Z. Indonesian Journal of Islamic Teaching, Vol.2 ,No.2.
- Nafisah, Aliyatin. 2014. Arti Penting Perpustakaan bagi Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat. Jurnal Perpustakaan Libraria, Vol.2 ,No.2.
- Permendikbud 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Saputra, Viro Dharma. 2020. Membangun Literasi Budaya Lokal Kepada Generasi Z Melalui Tradisi Weh-Wehan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi), Vol. 6, No.1.
- Sebagian isi dari tulisan esai ini adalah ide dan pendapat pribadi penulis.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 3.
BIOGRAFI PENULIS
 Nama : Alfa Deltia
Nama : Alfa Deltia
TTL : Bedeng Delapan, 27 Oktober 2000
Domisili : Kayu Aro Barat, Kerinci, Jambi
Pendidikan Terakhir : MA (Madrasah Aliyah)
Pengalaman :
- Pengurus FORSIS (Forum Studi Islam) Universitas Negeri Padang
- Anggota Luar Biasa PPIPM (Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa) Universitas Negeri Padang
Karya/Prestasi :
- 3 buku antologi puisi ber ISBN
- 3 karya tulis ilmiah
WA : 0822-8087-8365
Email : [email protected]
FB : Alfa Deltia
IG : @alfadeltia_